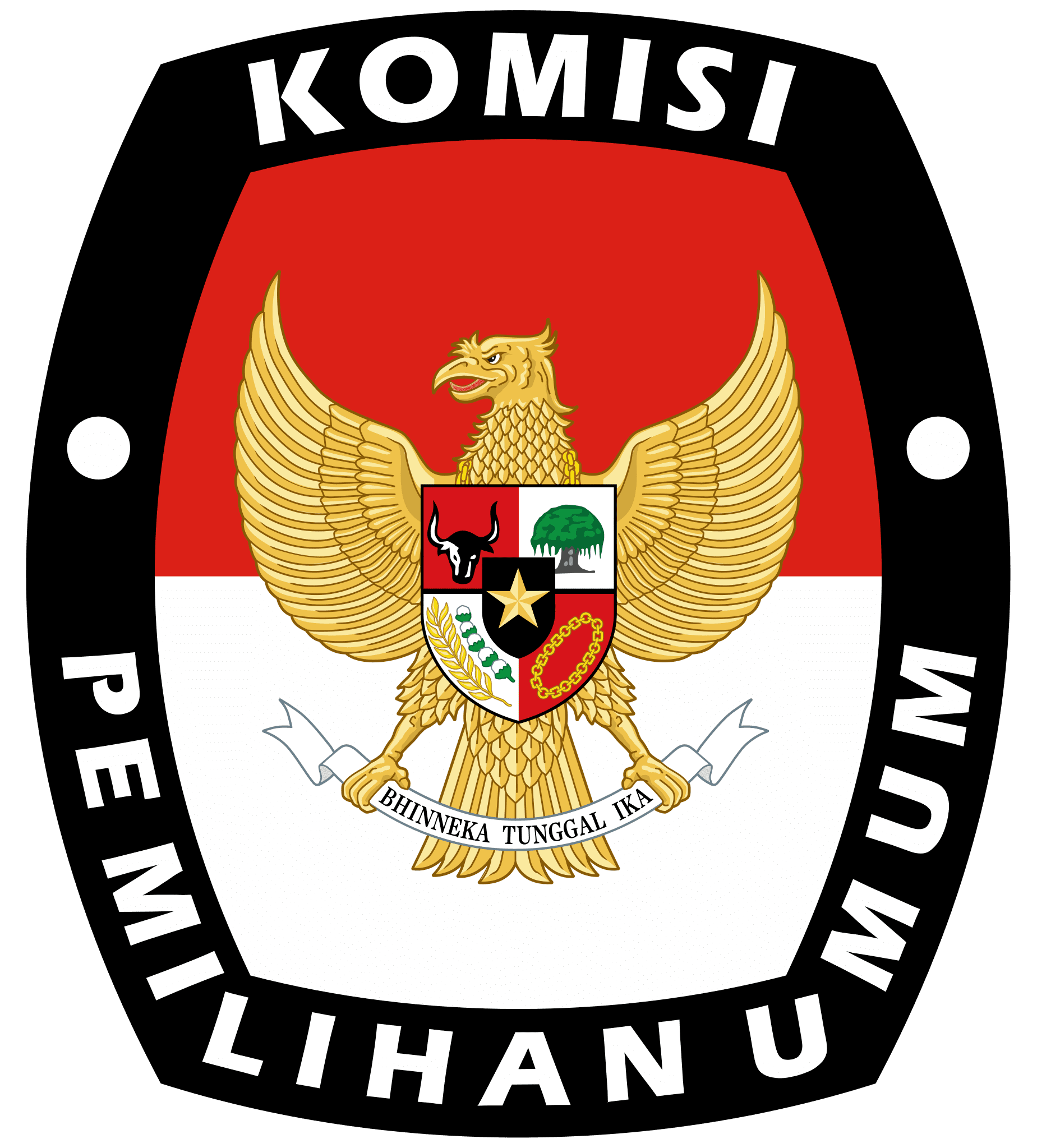Konferensi Meja Bundar: Tonggak Akhir Penyerahan Kedaulatan Indonesia dari Belanda
Wamena — Konferensi Meja Bundar (KMB) menjadi peristiwa penting dalam sejarah perjuangan diplomasi Indonesia. Diselenggarakan di Den Haag, Belanda, pada 23 Agustus hingga 2 November 1949, konferensi ini menjadi titik akhir dari perjuangan panjang Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan penuh dari Belanda setelah masa Revolusi Nasional Indonesia (1945–1949).
Pertemuan bersejarah ini dihadiri oleh tiga pihak utama, yakni delegasi Republik Indonesia, delegasi Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO) yang mewakili negara-negara federal bentukan Belanda di Indonesia, serta delegasi Kerajaan Belanda sebagai pihak kolonial. Di bawah pengawasan Komisi PBB untuk Indonesia (United Nations Commission for Indonesia/UNCI), konferensi ini menjadi momentum menentukan masa depan politik Indonesia pasca-proklamasi kemerdekaan.
Latar Belakang Terbentuknya KMB
Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Belanda berusaha kembali menguasai Nusantara melalui berbagai cara, termasuk agresi militer. Dua kali agresi militer — pada Juli 1947 dan Desember 1948 — menimbulkan tekanan internasional yang besar terhadap Belanda.
Sebagai tanggapan, Perjanjian Renville (1948) sempat menjadi solusi sementara, namun ketegangan tetap terjadi hingga akhirnya dunia internasional mendorong kedua belah pihak untuk mencari jalan damai. PBB melalui UNCI memediasi dan mengusulkan pertemuan formal untuk membahas penyerahan kedaulatan.
Sejarawan Dr. Anhar Gonggong menjelaskan, “Konferensi Meja Bundar bukan sekadar perundingan politik biasa, melainkan ujian bagi Indonesia dalam mempertahankan legitimasi kemerdekaannya di hadapan dunia internasional,”
(Anhar Gonggong, Sejarah Nasional Indonesia: Revolusi dan Diplomasi, 2010).
Delegasi dan Tokoh Penting KMB
Delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Drs. Mohammad Hatta, yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia. Sementara delegasi BFO diketuai oleh Sultan Hamid II dari Pontianak, dan delegasi Belanda dipimpin oleh Jan Herman van Maarseveen, Menteri Urusan Seberang Lautan Belanda.
Beberapa tokoh penting lain yang turut hadir dari pihak Indonesia antara lain Dr. Subandrio, Prof. Dr. Supomo, Mr. Ali Sastroamidjojo, dan Mohammad Roem. Mereka memainkan peran penting dalam negosiasi detail terkait kedaulatan, ekonomi, dan militer.
Dalam sebuah pidato yang dikutip dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Mohammad Hatta menegaskan tekad bangsa Indonesia:
“Kami datang ke meja perundingan bukan untuk meminta kemerdekaan, melainkan untuk menegaskan bahwa kemerdekaan telah kami miliki sejak 17 Agustus 1945.”
Kutipan itu menggambarkan sikap diplomatis namun tegas dari pihak Indonesia yang menolak anggapan bahwa kemerdekaan adalah hasil pemberian Belanda.
Baca juga: Mohammad Hatta: Sang Proklamator dan Bapak Koperasi Indonesia yang Visioner
Isi dan Hasil Perjanjian KMB
Konferensi Meja Bundar menghasilkan tiga dokumen utama, yaitu:
1. Persetujuan tentang Penyerahan Kedaulatan dari Belanda kepada Republik Indonesia Serikat (RIS).
2. Piagam Persetujuan Uni Indonesia-Belanda, yang menetapkan kerja sama di bidang ekonomi dan kebudayaan.
3. Kesepakatan mengenai masalah keuangan dan ekonomi, termasuk penyelesaian utang Hindia Belanda.
Isi utama dari perjanjian KMB antara lain:
Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat (RIS) paling lambat 30 Desember 1949.
RIS akan menjadi negara federal yang terdiri dari 16 negara bagian, termasuk Republik Indonesia (Yogyakarta) sebagai salah satu komponennya.
Indonesia bersedia menanggung sebagian utang pemerintahan Hindia Belanda sebelum 1942 yang bernilai ± 4,3 miliar gulden.
Pembentukan Uni Indonesia–Belanda yang bersifat sukarela dan bertujuan mempererat kerja sama ekonomi dan budaya.
Kendati hasil KMB di satu sisi dianggap kemenangan diplomasi, namun banyak kalangan menilai perjanjian itu sarat kompromi. Dalam buku Sejarah Diplomasi Indonesia (Rosihan Anwar, 1980), disebutkan:
“KMB menunjukkan kemampuan Indonesia berdiplomasi di panggung internasional, tetapi juga memperlihatkan tekanan politik dan ekonomi dari pihak kolonial.”
Dampak dan Kontroversi KMB
Pasca-KMB, Republik Indonesia Serikat resmi berdiri pada 27 Desember 1949, menandai berakhirnya secara resmi kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia. Namun, bentuk negara federal yang disepakati dalam KMB menimbulkan perdebatan di kalangan nasionalis.
Banyak tokoh, termasuk Ir. Soekarno, menilai bentuk negara federal adalah taktik Belanda untuk melemahkan persatuan Indonesia. Dalam pidato di Yogyakarta (1950), Soekarno mengatakan, “Negara federal adalah warisan kolonial yang harus kita satukan kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
(Sumber: Pidato Presiden Soekarno, 17 Agustus 1950, Arsip Nasional RI).
Akhirnya, setelah dinamika politik dan tekanan rakyat di berbagai daerah, Republik Indonesia Serikat dibubarkan pada 17 Agustus 1950, dan Indonesia kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Meski begitu, peran KMB tetap diakui sebagai titik balik penting. Sejarawan Belanda Prof. Willem Oltmans menulis dalam Indonesia: The Final Transfer of Power (1995):
“KMB merupakan kompromi historis — di mana Belanda terpaksa mengakui kekalahan kolonialnya, sementara Indonesia meneguhkan posisinya sebagai negara berdaulat di mata dunia.”
Makna KMB bagi Bangsa Indonesia
Konferensi Meja Bundar memberikan pelajaran penting bahwa diplomasi dan perjuangan intelektual dapat sejajar dengan perjuangan bersenjata. Keberhasilan Hatta dan tim delegasi menjadi simbol bahwa Indonesia mampu menunjukkan kedewasaan politik di kancah global.
Menurut Dr. Sri Margana, sejarawan Universitas Gadjah Mada (UGM):
“KMB adalah puncak dari strategi dua kaki perjuangan Indonesia — diplomasi di luar negeri dan perlawanan di dalam negeri. Tanpa keduanya, pengakuan kedaulatan mungkin tidak akan terjadi secepat itu.”
(Kompas, 27 Desember 2019).
Konferensi Meja Bundar menjadi babak akhir dari perjuangan kemerdekaan Indonesia melawan kolonialisme Belanda. Walau penuh kompromi, hasil KMB membuka jalan bagi pengakuan kedaulatan secara internasional. Momentum ini menegaskan kecerdikan para pendiri bangsa dalam memperjuangkan kemerdekaan melalui diplomasi, bukan sekadar peperangan.
Sebagaimana dikatakan Mohammad Hatta seusai penandatanganan perjanjian di Den Haag:
“Kita boleh berbeda jalan dalam perjuangan, tetapi tujuan kita satu — Indonesia yang merdeka dan berdaulat sepenuhnya.”
(Sumber: ANRI, 1949).
![]()
![]()
![]()