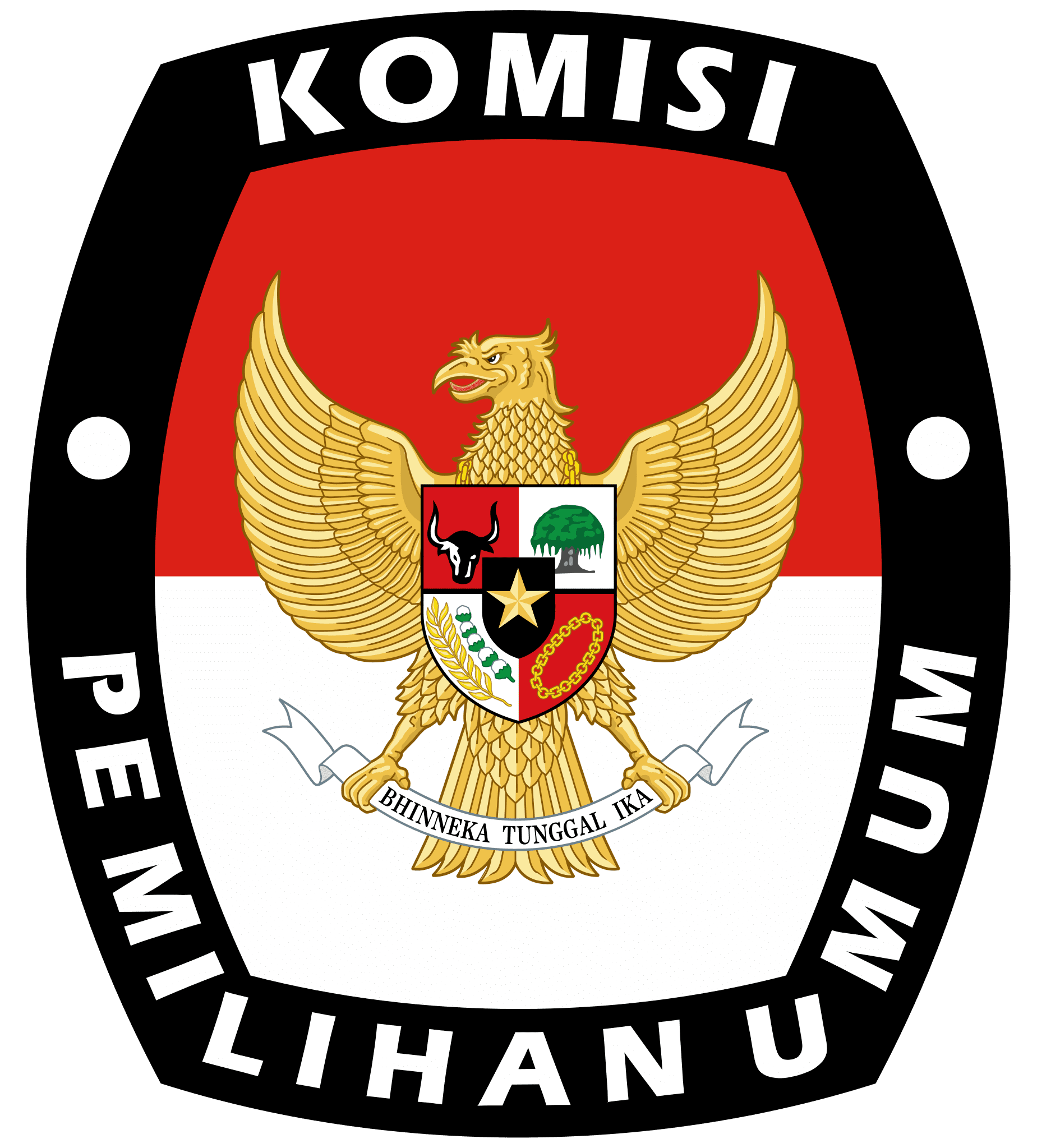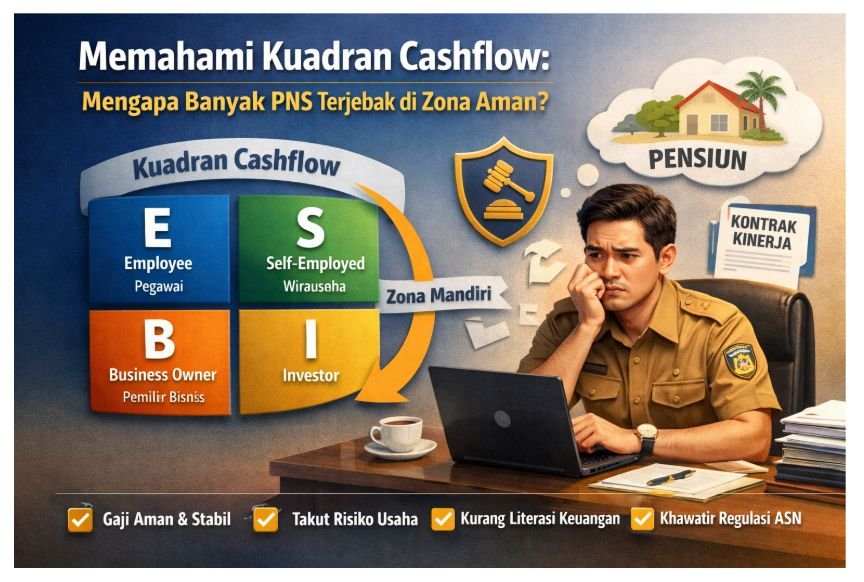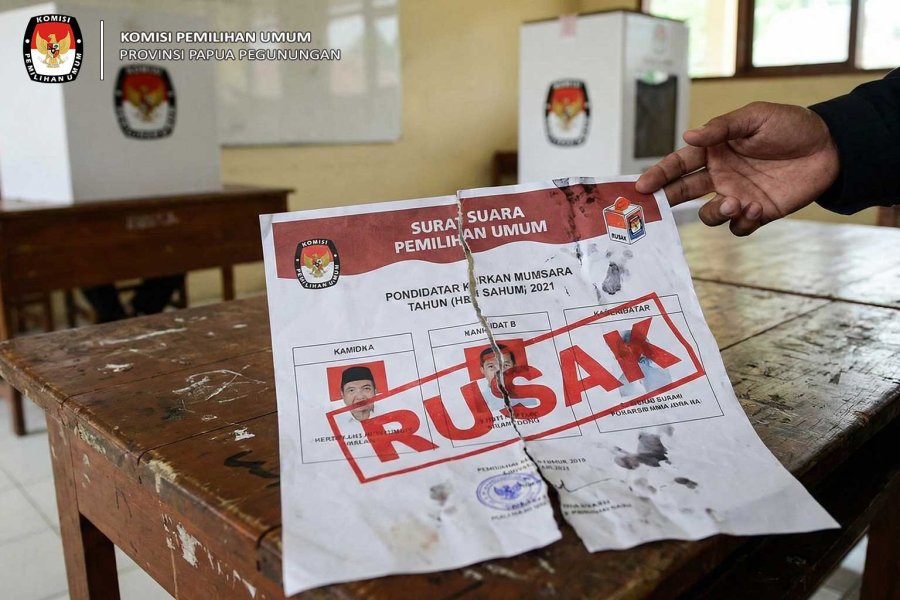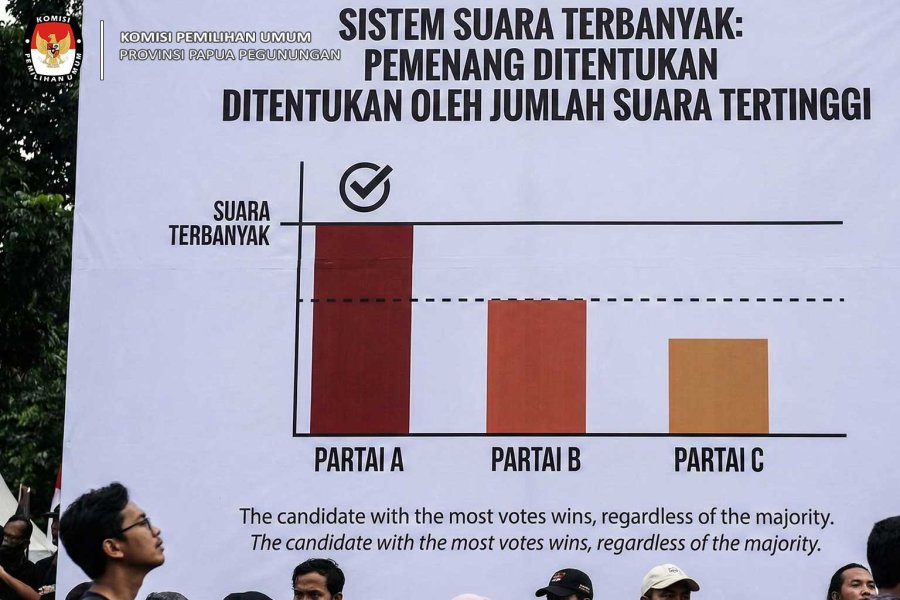Himpunan Mahasiswa Islam: Sejarah, Perjuangan, dan Perannya dalam Menjaga Demokrasi Indonesia
Wamena - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) lahir ketika Republik Indonesia masih berada pada fase paling rapuh dalam sejarahnya. Negara belum sepenuhnya mapan, perang mempertahankan kemerdekaan masih berlangsung, dan kekuasaan belum sepenuhnya berada di tangan bangsa sendiri. Di tengah situasi revolusi fisik itulah, sekelompok mahasiswa memilih jalan perjuangan yang berbeda. Mereka tidak mengangkat senjata, melainkan membangun organisasi. Mereka meyakini bahwa kemerdekaan tidak cukup dipertahankan dengan kekuatan militer semata. Demokrasi membutuhkan manusia yang berpikir jernih, beretika, dan bertanggung jawab. Pilihan ini menunjukkan kesadaran bahwa masa depan republik sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia, terutama kaum terpelajar di lingkungan kampus, demi mempertinggi derajat rakyat dan bangsa Indonesia. Dari konteks inilah HMI lahir dan kemudian bertahan sebagai salah satu organisasi mahasiswa paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia Lahir di Tengah Revolusi Fisik Himpunan Mahasiswa Islam berdiri pada 5 Februari 1947 di Yogyakarta. Pada masa itu, Indonesia masih berjuang mempertahankan kemerdekaan dari Belanda. Agresi militer terus berlangsung, pemerintahan berpindah-pindah, dan kampus-kampus tidak berjalan normal. Aktivitas akademik kerap terhenti oleh situasi perang yang tidak menentu. Dalam kondisi seperti itu, Lafran Pane melihat persoalan mendasar. Mahasiswa Islam tersebar di berbagai kota tanpa memiliki wadah bersama. Mereka memiliki semangat kebangsaan, tetapi belum terorganisir secara ideologis dan intelektual. Padahal, republik yang baru lahir sangat membutuhkan tenaga terdidik untuk mempertahankan sekaligus mengisi kemerdekaan. HMI hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut. Sejak awal, organisasi ini tidak dimaksudkan sebagai alat politik praktis. Tujuannya jelas dan tegas: mempertahankan Negara Republik Indonesia serta mengembangkan ajaran Islam. Kedua tujuan ini tidak dipertentangkan, melainkan dipadukan. Islam diposisikan sebagai sumber etika perjuangan, bukan sebagai alat perebutan kekuasaan. Baca juga: Lafran Pane: Islam, Kebangsaan, dan Akar Demokrasi Indonesia Perubahan Tujuan dan Pendewasaan Gerakan Seiring perjalanan waktu, tujuan HMI mengalami penyesuaian. Pada Kongres Pertama HMI di Yogyakarta, 30 November 1947, rumusan tujuan diubah menjadi menegakkan dan mengembangkan agama Islam serta mempertinggi derajat rakyat dan Negara Republik Indonesia. Perubahan ini mencerminkan kesadaran akan konteks perjuangan bangsa yang saat itu masih berada dalam masa revolusi fisik. Selanjutnya, pada Kongres IV HMI di Bandung, 4 Oktober 1955, tujuan organisasi kembali diperbarui menjadi ikut mengusahakan terbentuknya manusia akademis, pencipta, dan pengabdi yang bernafaskan Islam. Perubahan ini menandai pergeseran orientasi HMI, dari semata-mata bertahan dalam situasi perang menuju fokus pada pembinaan sumber daya manusia. Rumusan tersebut kemudian disempurnakan pada Kongres X HMI di Palembang menjadi: “Terbinanya insan akademis, pencipta, dan pengabdi yang bernafaskan Islam serta bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhai Allah SWT.” Rumusan inilah yang bertahan hingga hari ini dan menjadi identitas ideologis HMI. HMI dan Pendidikan Kader Sejak awal, HMI tidak dibangun sebagai organisasi massa, melainkan sebagai organisasi kader. Pendidikan menjadi jantung gerakan. Diskusi, latihan kepemimpinan, dan tradisi membaca buku dijaga secara turun-temurun. Kader HMI dilatih untuk berpikir sistematis dan kritis. Mereka diajak memahami sejarah bangsa, teori politik, pemikiran Islam, serta realitas sosial. Demokrasi tidak diajarkan sebagai slogan semata, melainkan dipraktikkan melalui musyawarah, perdebatan gagasan, dan pengambilan keputusan kolektif. Model kaderisasi seperti ini membuat HMI mampu bertahan melewati berbagai perubahan rezim. Banyak organisasi mahasiswa lahir dan tenggelam mengikuti momentum politik, sementara HMI tetap hidup karena fondasinya adalah pembinaan jangka panjang. Baca Juga: Milad Muhammadiyah ke-113 : Jejak Perjuangan, Pendidikan, dan Dakwah Pencerahan bagi NKRI HMI pada Masa Revolusi dan Awal Republik Pada masa revolusi fisik dan awal kemerdekaan, kader-kader HMI terlibat aktif di berbagai sektor. Ada yang membantu diplomasi, ada yang masuk ke birokrasi, dan ada pula yang tetap berada di kampus sebagai pendidik serta penggerak intelektual. Peran ini mendapat pengakuan luas. Pada peringatan Milad pertama HMI, 6 Februari 1948 di Yogyakarta, Jenderal Soedirman menyampaikan pernyataan yang kemudian sering dikutip, bahwa HMI bukan sekadar himpunan mahasiswa Islam, melainkan harapan masyarakat Indonesia. Pernyataan ini menunjukkan bahwa sejak awal HMI dipandang sebagai bagian dari perjuangan nasional. Baca Juga: Bayang-Bayang G30S/PKI: Dua Saudara dalam Satu Rahim, Berbeda Jalan Politik HMI dan Demokrasi Parlementer Pada era demokrasi parlementer, Indonesia memasuki masa penuh ketegangan ideologis. Nasionalisme, Islam, dan komunisme saling berhadapan dalam ruang politik. HMI berada pada posisi yang tidak mudah. Di satu sisi, ia menolak komunisme. Di sisi lain, ia juga menolak menjadi alat partai politik tertentu. Sikap ini membuat HMI kerap berada di bawah tekanan, terutama ketika berhadapan dengan CGMI, organisasi mahasiswa yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia. Ketegangan ini mencapai puncaknya pada akhir masa Orde Lama, ketika HMI sempat terancam dibubarkan. Namun, tekanan tersebut justru membentuk karakter independen HMI. Organisasi ini mempertahankan posisinya sebagai organisasi mahasiswa Islam yang berkomitmen pada negara dan demokrasi konstitusional. Baca Juga: NU, Demokrasi, dan Indonesia Merdeka : Peran 100 Tahun Nahdlatul Ulama HMI pada Masa Orde Baru Memasuki era Orde Baru, situasi politik kembali berubah. Negara menjadi sangat kuat, ruang demokrasi menyempit, dan gerakan mahasiswa dibatasi. Banyak organisasi memilih beradaptasi sepenuhnya atau akhirnya dibubarkan. Pada masa ini, HMI dipimpin oleh Nurcholish Madjid (Cak Nur) selama dua periode, 1966–1971. Di bawah kepemimpinannya, HMI mengalami perkembangan pemikiran yang signifikan. Cak Nur mendorong pembaruan cara berpikir tentang Islam dan keindonesiaan. Ia menggagas Nilai Dasar Perjuangan (NDP) HMI yang disahkan pada Kongres X di Palembang. Dokumen ini menjadi fondasi ideologis HMI hingga hari ini. Dari periode ini pula muncul generasi intelektual Muslim yang berpengaruh di ruang publik nasional. Setelah Cak Nur, kepemimpinan Akbar Tanjung pada periode 1971–1974 memperkuat konsolidasi organisasi dan memperluas jaringan kaderisasi. Pada masa beliau inilah terbentuk juga Kelompok Cipayung, yang merupakan forum silaturahmi dan berdiskusi organisasi gerakan mahasiwa, HMI semakin menguat secara struktural. Konflik Internal dan Dualisme Organisasi Memasuki era 1980-an, hubungan HMI dengan pemerintah kembali memanas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 yang mewajibkan semua organisasi berasas Pancasila memicu perdebatan tajam di internal HMI. Puncaknya terjadi pada Kongres XVI HMI tahun 1986 di Padang. Organisasi kemudian terpecah. Sebagian kader menyelenggarakan kongres tandingan di Kaliurang dan Wonosari, guna membentuk Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) HMI. Sejak saat itu, HMI berada dalam kondisi dualisme. Meskipun terpecah, kedua kubu HMI tetap berakar pada tradisi kaderisasi yang sama. Dalam banyak hal, mereka tetap berdekatan dan bahkan kerap berkolaborasi dalam isu-isu kebangsaan. Hal ini diperkuat dengan dipertemukannya Harry Azhar Aziz dan Eggy Sudjana selaku tokoh penting dalam terpecahya HMI, pertemuan keduanya terjadi pada Konggres XXXI HMI MPO di Sorong Papua Barat Daya awal 2018. HMI dan Era Reformasi Reformasi 1998 membuka ruang baru bagi demokrasi Indonesia. Kader-kader HMI terlibat aktif dalam gerakan mahasiswa yang mendorong tumbangnya rezim Orde Baru. Sejumlah tokoh reformasi tercatat sebagai kader atau alumni HMI, di antaranya Amien Rais, Yusril Ihza Mahendra, Anas Urbaningrum dan Ubedilah Badrun. Pasca reformasi, tantangan kembali berubah. Demokrasi prosedural berjalan, pemilu dilaksanakan secara rutin, tetapi kualitas demokrasi menghadapi persoalan serius seperti politik uang, polarisasi, dan menguatnya pragmatisme politik. Dalam konteks ini, peran HMI kembali diuji: apakah ia tetap menjadi ruang pendidikan etika publik atau justru sekadar menjadi jaringan kekuasaan. Sumbangsih HMI bagi Demokrasi Indonesia Kontribusi HMI tidak dapat diukur hanya dari satu sektor. Peran tersebut tersebar di dunia akademik, birokrasi, politik, dan masyarakat sipil. Banyak dosen, peneliti, birokrat, dan aktivis lahir dari proses kaderisasi HMI. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi mahasiswa dapat memberi dampak lintas generasi. Demokrasi tidak hanya dijaga di bilik suara, tetapi juga dirawat melalui pendidikan, diskusi, dan pembentukan karakter. Catatan Kritis terhadap HMI Tentu, tidak semua pihak sepakat dengan glorifikasi terhadap HMI. Organisasi ini bukan satu-satunya organisasi mahasiswa, dan tidak semua kadernya konsisten menjaga etika demokrasi. Sebagian kecil justru terjebak dalam pragmatisme politik. Kritik ini sah dan perlu didengar. Sejarah tidak boleh dibaca secara tunggal. Namun, kelebihan HMI terletak pada kontinuitasnya. Ia hadir sejak masa revolusi hingga hari ini, sebuah rentang sejarah yang jarang dimiliki organisasi mahasiswa lain. HMI dan Masa Depan Demokrasi Demokrasi Indonesia hari ini membutuhkan pembaruan etika, bukan hanya perbaikan regulasi. HMI memiliki modal sejarah untuk terus berkontribusi jika kembali menegaskan diri sebagai ruang pendidikan kader yang kritis dan independen. Lafran Pane memulai semua ini dalam kondisi negara yang jauh lebih sulit daripada hari ini. Tantangan zaman memang berubah, tetapi prinsip dasarnya tetap sama: demokrasi hanya akan hidup jika dirawat oleh manusia yang berilmu, beretika, dan berani bertanggung jawab.