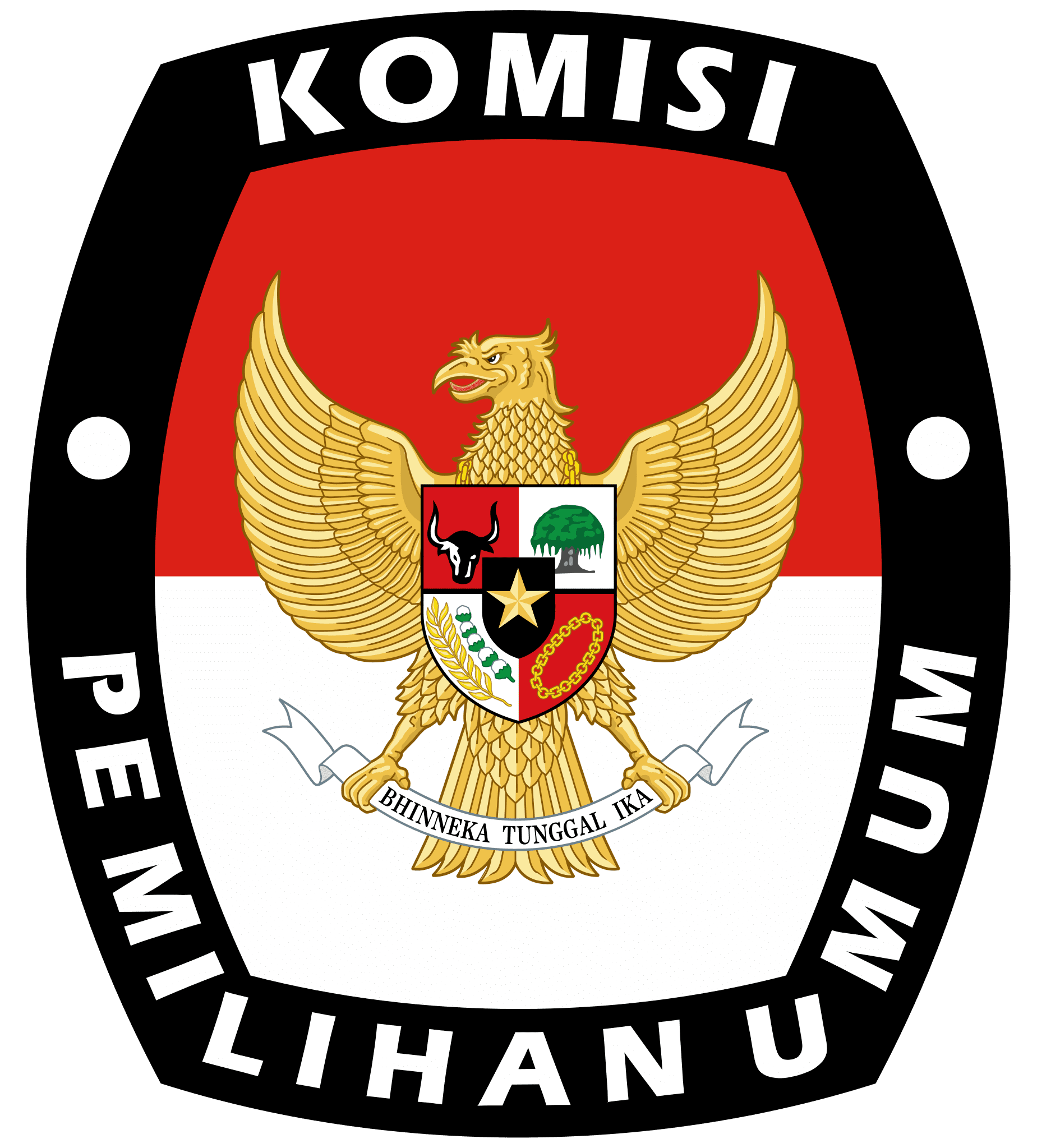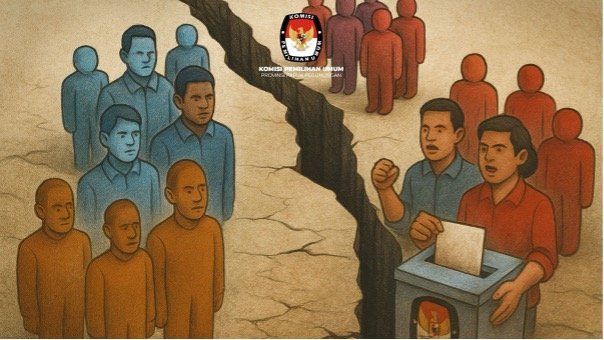
Memahami Polarisasi Politik: Definisi, Faktor Pemicu, dan Cara Mengatasinya
Wamena — Istilah Polarisasi Politik dijelaskan oleh Ibnu Chaerul Mansyur dalam bukunya berjudul “Polarisasi Politik di Indonesia 2014-2019: Sebuah Kajian Pustaka” merujuk pada kondisi ketika masyarakat terpecah menjadi dua atau lebih kubu/kelompok dalam pandangan politik, yang mana dalam perpecahan ini muncul rasa saling tidak percaya dan kebencian, sehingga memunculkan permusuhan. Polarisasi politik tidak hanya berbentuk perbedaan pendapat, namun juga merujuk pada sikap emosional, fanatisme, penolakan terhadap argumen lawan, dan munculnya stigma negatif terhadap kelompok lain yang dianggap “berseberangan”. Fenomena ini bukan hal baru, namun saat ini terasa lebih kuat karena penyebaran informasi berjalan lebih cepat. Informasi yang tersebar juga tidak selalu terverifikasi kebenarannya.
Perbedaan pilihan politik mudah berubah menjadi perselisihan personal, bahkan memicu saling serang di media sosial. Namun perlu diketahui bahwa polarisasi tidak selalu berbahaya selama perbedaan pendapat tetap berada dalam koridor etika dan fakta yang sesuai. Berubah menjadi ancaman ketika masyarakat menutup diri dari dialog, menolak data, serta menjadikan politik sebagai identitas emosional, bukan ruang rasional. Oleh karena itu, literasi digital dan keberimbangan informasi menjadi faktor penting untuk mencegah polarisasi berubah menjadi ancaman persatuan bangsa. Masyarakat harus menjaga persatuan, mengutamakan musyawarah, serta tidak mempersonalisasi pilihan politik dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat.
Baca juga: Politik: Makna, Fungsi, dan Dampaknya bagi Kehidupan Rakyat
Penyebab Utama Polarisasi Politik
Polarisasi politik semakin mudah muncul dan mengeras di tengah masyarakat, menjelang kontestasi politik nasional. Kondisi ini bukan sekadar soal perbedaan pilihan, tetapi juga karena dipicu oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan, mulai dari ideologi, dinamika elite, hingga pengaruh media digital. Berikut beberapa faktor yang memicu polarisasi politik antara lain;
- Perbedaan Ideologi dan Kepentingan Politik. Saat pemilu atau ketika muncul perdebatan tentang kebijakan publik, masyarakat cenderung terbelah mengikuti pandangan dan afiliasi masing-masing. Kontestasi kekuasaan yang keras membuat opini publik mudah terseret dalam “persaingan” kubu.
- Peran Media dan Media Sosial. Algoritma platform digital menciptakan ruang gema (echo chamber), yang membuat pengguna hanya menerima informasi searah tanpa menerima pandangan alternatif lain. Sehingga marak terjadi penyebaran hoax, disinformasi, bahkan konten provokatif turut memperkuat jarak antar kelompok yang terpolarisasi.
- Manipulasi Emosi dan Identitas kampanye berbasis identitas, SARA, hingga narasi kebencian. Narasi berbasis ketakutan atau kebencian dinilai efektif menggerakkan dukungan kepada peserta pemilu, namun tentu saja meninggalkan residu sosial yang sulit dipulihkan dalam waktu singkat.
- Kurangnya Literasi Politik dan Digital. Banyak masyarakat yang menerima pesan berantai atau unggahan viral tanpa memverifikasi konteks maupun sumbernya. Hal ini menyebabkan opini publik terbentuk dari persepsi yang belum tentu jelas kebenarannya.
- Persaingan Elit Politik. Konflik antar elit politik, partai politik, maupun kubu pendukung sering bergeser dari isu kebijakan menjadi serangan personal, lalu dikonsumsi ulang oleh publik hingga menciptakan jarak sosial.
Perlu diingatkan bahwa polarisasi tidak selalu berujung pada konflik terbuka, namun jika dibiarkan tanpa edukasi publik dan ruang dialog yang terbuka, dampaknya bisa mengganggu kohesi sosial serta menurunkan kualitas demokrasi. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tetap kritis, tidak mudah terpancing provokasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa diatas kepentingan-kepentingan kelompok.
Baca juga: Politik Identitas: Pengertian, Dampak, dan Tantangannya bagi Demokrasi Indonesia
Dampak Polarisasi Politik terhadap Demokrasi
Polarisasi politik yang semakin terasa di ruang publik dinilai membawa dampak serius terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Kondisi ini bukan sekadar perbedaan pandangan politik, tetapi justru berkembang menjadi keterbelahan sosial yang mempengaruhi hubungan sosial antar warga. Dampak polarisasi politik dapat bersifat sosial, politik, hingga psikologis, antara lain;
- Menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi demokrasi. Ketika masyarakat terbelah dalam sudut pandang politik yang ekstrem, setiap kebijakan atau keputusan negara kerap dianggap bias dan tidak mewakili seluruh kepentingan rakyat. Kondisi ini membuat legitimasi pemerintah mudah dipertanyakan. Somer, McCoy, Murat, Jennifer (2018), dalam bukunya yang berjudul "Deja Vu? Polarization and Endangered Democracies in the 21st Century" menjelaskan bahwa masyarakat yang terpolarisasi akan kehilangan kepercayaan terhadap lembaga-lembaga negara. Menurunnya kepercayaan masyarakat secara otomatis menyebabkan dukungan masyarakat terhadap norma dan demokrasi ikut menurun. Masyarakat akan sulit untuk bertindak berdasarkan prinsip moral dengan mengacu pada kebenaran atau bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang ada ketika hal tersebut bertentangan dengan kepentingan partai.
- Terganggunya kohesi sosial sehingga masyarakat saling curiga dan mudah terprovokasi. Dalam Jurnal Ilmiah yang berjudul “Upaya Pencegahan Polarisasi Politik di Tahun Pemilu 2024” menjelaskan bahwa polarisasi politik membuat warga saling curiga, menjaga jarak, hingga mudah terpancing perdebatan emosional. Perbedaan pilihan politik yang seharusnya menjadi hal biasa dalam demokrasi, berubah menjadi pemisah hubungan keluarga, pertemanan, bahkan komunitas (Rianadiwa, dkk, 2024).
- Diskursus publik menjadi tidak sehat, tidak rasional, dan penuh ujaran kebencian. Dalam ranah komunikasi publik, ruang diskusi semakin sulit berlangsung dengan sehat. Wacana politik dipenuhi ujaran kebencian, serangan personal, dan informasi yang belum terverifikasi. Pandangan berbeda tidak lagi dibahas secara rasional, melainkan dijadikan dasar untuk melabeli dan menyerang kelompok tertentu.
- Menghambat dialog dan kompromi. Dalam buku berjudul "Democracies Divided: The Global Challenge of Political Polarization" Polarisasi Politik yang terbentuk memperburuk kompromi, konsensus, interaksi. Serta menipisnya toleransi bagi bagi individu di tengah masyarakat hingga aktor politik di kedua kelompok/kubu berbeda. Polarisasi Politik menyebabkan kerusakan hingga melemahkan penghormatan terhadap norma-norma demokrasi karena proses dasar legislatif dan fungsi peradilan dilemahkan. Perlu diketahui bahwa, demokrasi bertumpu pada musyawarah serta kesediaan untuk mendengarkan pihak lain. Ketika kompromi dianggap sebagai kelemahan, kebijakan publik berisiko tersandera kepentingan kelompok dan bukan kepentingan bersama.
- Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mengancam stabilitas politik dan keamanan negara. Konflik sosial yang dimulai dari perbedaan opini dapat bergeser menjadi konflik horizontal jika tidak ditangani dengan edukasi, literasi, serta komunikasi politik yang bijak.
Polarisasi Politik di Era Media Sosial
Platform digital saat ini tidak hanya mempengaruhi cara masyarakat mendapatkan informasi politik, tetapi juga berpengaruh pada pembentukan cara berpikir, bersikap, dan berinteraksi dalam melihat perbedaan pandangan. Media sosial memiliki andil besar dalam mempercepat dan memperluas polarisasi, yang disebabkan karena;
- Informasi menyebar sangat cepat tanpa kontrol kebenaran. Setiap unggahan dapat viral dalam hitungan menit, sekalipun belum terbukti kebenarannya. Alhasil, opini publik sering terbentuk bukan berdasarkan data, melainkan narasi yang paling ramai dibicarakan.
- Algoritma menampilkan konten sesuai preferensi pengguna, sehingga menciptakan ruang diskusi yang homogen. Konten yang muncul di FYP (for your page)/beranda pengguna umumnya disesuaikan dengan minat, jejak interaksi, dan preferensi politik. Kondisi ini menciptakan ruang diskusi yang homogen, dimana pengguna merasa pandangannya paling benar karena jarang bertemu argumen alternatif yang berbeda secara proporsional.
- Munculnya konten provokatif, hoax, dan propaganda politik yang disebar akun anonim atau buzzer. Banyak di antara informasi yang beredar di masyarakat diproduksi dan disebarkan oleh akun anonim, buzzer, atau pihak yang memiliki agenda tertentu. Konten semacam ini seringkali bersifat emosional, menyerang identitas, dan memicu reaksi tanpa analisis.
- Pengguna lebih mudah menyerang lawan pendapat tanpa etika dan data yang valid. Diskusi publik pun bergeser dari argumentasi substantif menjadi pertarungan opini yang penuh sentimen dan kecurigaan.
Oleh karena itu, literasi digital adalah kunci untuk meredam dampak polarisasi di era digitalisasi informasi yang semakin pesat. Masyarakat didorong untuk menjadikan media sosial sebagai ruang dialog, bukan justru sebagai arena konflik yang memperbesar perpecahan antar warga.
Baca juga: Apa Itu Buzzer Politik ? Ini Penjelasan, Fungsi, dan Cara Kerjanya
Contoh Polarisasi Politik di Indonesia
Perbedaan pandangan yang seharusnya menjadi bagian wajar dari demokrasi, justru berkembang menjadi pertentangan tajam hingga memecah relasi sosial. Fenomena polarisasi politik dapat terlihat jelas pada beberapa momen politik nasional, antara lain;
- Perbedaan pendapat tajam dalam kontestasi pemilu dan pilkada di mana dukungan politik berubah menjadi sentimen emosional. Tidak sedikit masyarakat yang terjebak dalam dikotomi ekstrem, seolah hanya ada “kami” dan “mereka”. Perbedaan pilihan sering kali dianggap sebagai alasan untuk memutus hubungan sosial, bahkan di lingkungan keluarga.
- Konflik opini di ruang digital mengenai kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah kerap menjadi bahan perdebatan panjang di media sosial, namun tidak jarang malah bergeser menjadi serangan personal.
- Tagar tandingan, perdebatan panas, dan serangan personal antar kelompok pendukung. Tagar tandingan yang saling bermunculan, memicu eskalasi opini yang berujung pada persaingan antar kelompok pendukung.
- Konflik identitas yang mengarah pada pelabelan, stigma, dan diskriminasi verbal. Penyematan istilah tertentu menjadi senjata politik yang dapat memperlebar jurang perbedaan antara kelompok yang terpecah. Meski terjadi di ruang verbal, dampaknya nyata pada kehidupan sosial seperti munculnya rasa curiga, sinisme, dan fanatisme mulai meminggirkan sikap rasional.
Cara Meredam dan Mencegah Polarisasi Politik
Di tengah meningkatnya polarisasi politik, berbagai langkah dinilai perlu dilakukan untuk meredam ketegangan dan mengembalikan ruang publik yang sehat. Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui beberapa langkah, antara lain;
- Meningkatkan literasi politik dan digital sejak pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Pendidikan politik menjadi salah satu kunci utama. Literasi politik dan digital perlu ditanamkan sejak bangku sekolah hingga perguruan tinggi agar masyarakat mampu memilah informasi dan tidak mudah terseret opini menyesatkan.
- Mengutamakan dialog dan ruang diskusi yang sehat berbasis data, bukan emosi. Ruang diskusi harus memberi tempat pada argumen, bukan emosi. Pendapat yang saling bersebrangan dan berbeda tidak seharusnya menjadi bahan permusuhan, tetapi harusnya dimaknai sebagai bagian dari proses perkembangan demokrasi.
- Mendorong media dan tokoh publik bersikap independen dan edukatif, bukan provokatif.
- Memperkuat etika bermedia sosial, termasuk verifikasi fakta sebelum berbagi informasi. Budaya verifikasi informasi di media sosial harus diperkuat sebagai etika minimum, termasuk menahan diri untuk tidak membagikan konten yang belum teruji kebenarannya.
- Menghidupkan nilai-nilai persatuan nasional, seperti toleransi, kebhinekaan, dan musyawarah.
![]()
![]()
![]()