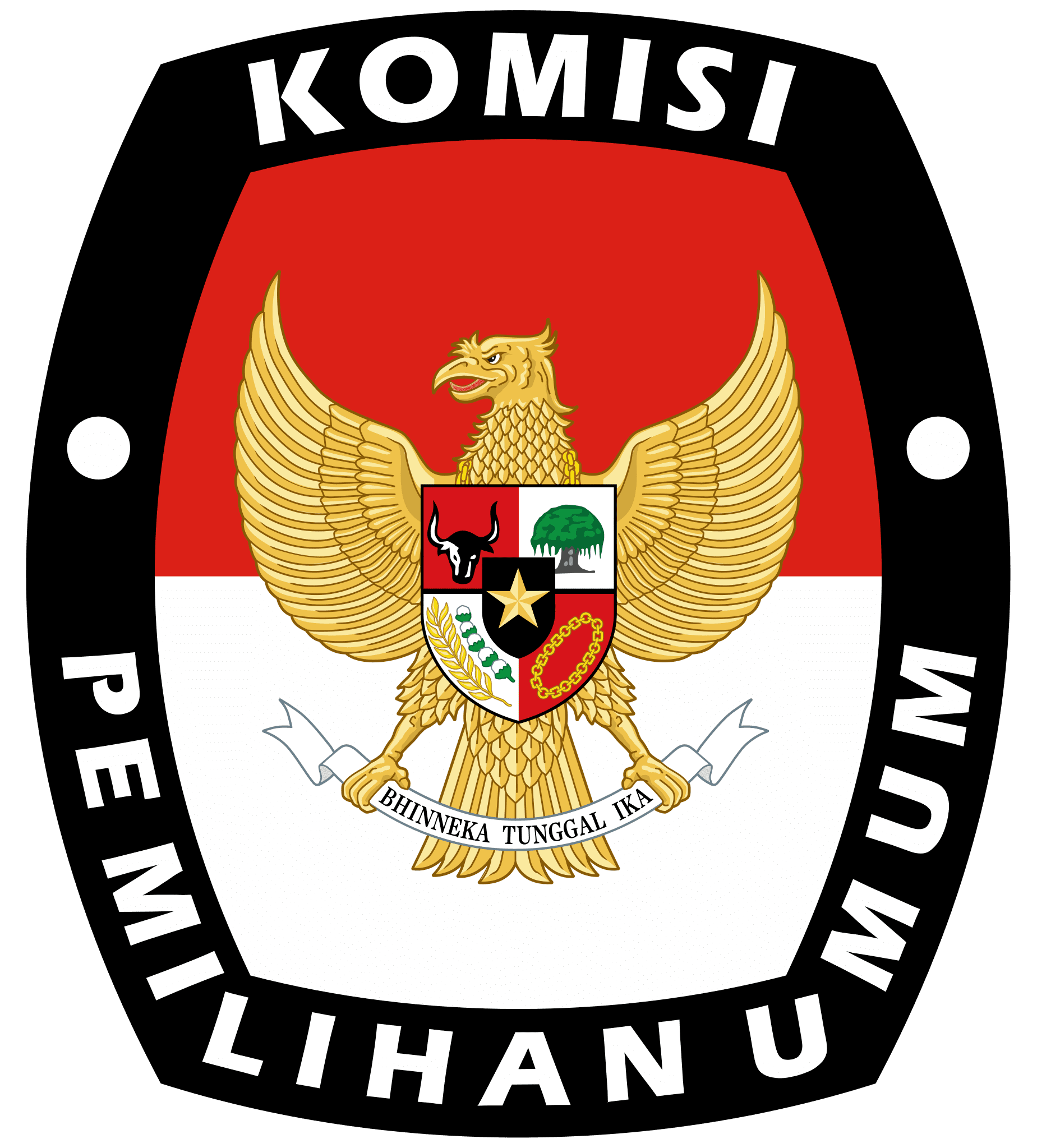Mengungkap Fakta Agresi Militer Belanda I 1947: Serangan Kolonial yang Mengguncang Republik Muda Indonesia
Wamena — Agresi Militer Belanda I pada 21 Juli 1947 menjadi salah satu babak paling kelam dalam sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Serangan besar-besaran yang dilancarkan Belanda ke wilayah Republik Indonesia dilakukan dengan dalih “aksi polisionil”, padahal tujuannya jelas — merebut kembali kendali atas Nusantara yang baru dua tahun merdeka.
Sejarawan Universitas Gadjah Mada, Dr. Asvi Warman Adam, dalam wawancaranya dengan Kompas (2017) menjelaskan, “Istilah ‘aksi polisionil’ hanyalah eufemisme dari agresi militer. Belanda ingin menutupi tindakan perang terbuka terhadap negara yang baru berdiri.”
Latar Belakang Agresi Militer Belanda I
Pasca Perjanjian Linggarjati (15 November 1946), Belanda dan Indonesia sepakat bahwa Belanda mengakui kekuasaan de facto Republik Indonesia yang meliputi Jawa, Madura, dan Sumatra. Namun, Belanda masih ingin membentuk negara-negara bagian dalam konsep “Republik Indonesia Serikat” di bawah kendalinya.
Ketegangan meningkat ketika Belanda menuduh Indonesia melanggar perjanjian dengan memperluas wilayahnya. Pada 21 Juli 1947, tanpa pernyataan perang resmi, Belanda melancarkan serangan udara dan darat ke beberapa wilayah penting di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatra Timur.
Menurut catatan dalam Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), operasi militer ini dinamai Operatie Product, yang berarti “Operasi Produksi”, karena Belanda menargetkan daerah-daerah penghasil komoditas ekspor seperti perkebunan tembakau dan karet.
Baca juga: Mengungkap Peristiwa Rengasdengklok: Detik-Detik Penting Menjelang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
Serangan dan Perlawanan di Lapangan
Serangan pertama Belanda dimulai dari basis militernya di Batavia (Jakarta) dan Surabaya, menyasar kota-kota seperti Semarang, Solo, dan Malang. Dalam waktu singkat, pasukan Belanda berhasil merebut wilayah yang kaya sumber daya.
Namun, pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak tinggal diam. Mereka melakukan perlawanan sengit dengan taktik perang gerilya. Panglima Besar Jenderal Soedirman memerintahkan agar pasukan mempertahankan setiap jengkal tanah dengan sistem pertahanan rakyat semesta.
Dalam memoarnya yang dikutip oleh Pusat Sejarah TNI (2016), Soedirman menulis, “Kita tidak mungkin melawan Belanda dengan kekuatan senjata semata. Tapi semangat dan tekad rakyat adalah senjata yang tak terkalahkan.”
Reaksi Internasional dan Tekanan PBB
Aksi militer Belanda memicu kecaman luas dari dunia internasional. Negara-negara Asia seperti India, Australia, dan Mesir menilai tindakan Belanda bertentangan dengan semangat dekolonisasi.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pun turun tangan. Pada 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang meminta gencatan senjata segera dilakukan. Sebuah Komisi Jasa Baik (Committee of Good Offices) dibentuk untuk menengahi konflik antara Indonesia dan Belanda.
Komisi ini terdiri dari tiga negara: Australia (mewakili Indonesia), Belgia (mewakili Belanda), dan Amerika Serikat sebagai pihak netral. Upaya diplomasi pun mulai dilakukan di atas kapal perang USS Renville di Teluk Jakarta.
Baca juga: Tragedi Bandung Lautan Api: Kisah Heroik Rakyat Bandung Membakar Kotanya Demi Kemerdekaan
Lahirnya Perjanjian Renville (1948)
Negosiasi panjang menghasilkan Perjanjian Renville yang ditandatangani pada 17 Januari 1948. Perjanjian ini mempertegas garis demarkasi antara wilayah Republik Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Namun, hasilnya sangat merugikan pihak Indonesia karena kehilangan banyak wilayah strategis.
Perdana Menteri Amir Sjarifuddin yang menandatangani perjanjian tersebut mendapat kritik tajam dari dalam negeri. Ia akhirnya mengundurkan diri karena dianggap terlalu kompromistis terhadap Belanda.
Meski begitu, menurut sejarawan Prof. Taufik Abdullah dalam buku Sejarah Nasional Indonesia (Balai Pustaka, 2010), “Perjanjian Renville menjadi bukti bahwa diplomasi Indonesia tetap berjalan di tengah tekanan militer. Ini menunjukkan bahwa perjuangan Indonesia bukan hanya lewat senjata, tetapi juga lewat meja perundingan.”
Dampak Sosial dan Ekonomi dari Agresi Militer Belanda I
Agresi militer menyebabkan ribuan korban jiwa, kehancuran ekonomi, dan penderitaan rakyat. Banyak warga desa yang mengungsi ke pedalaman untuk menghindari serangan udara Belanda. Infrastruktur seperti rel kereta api dan jembatan rusak berat.
Menurut Laporan Komisi HAM PBB tahun 1948, sekitar 150.000 penduduk sipil kehilangan tempat tinggal akibat operasi militer tersebut. Meski demikian, semangat perlawanan rakyat tidak padam.
Dari sisi ekonomi, blokade laut yang dilakukan Belanda memutus jalur ekspor Indonesia, sehingga negara kehilangan banyak sumber devisa. Namun, di sisi lain, agresi ini justru memperkuat solidaritas nasional dan mempererat hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara Asia yang mendukung kemerdekaan.
Agresi yang Menyulut Semangat Kemerdekaan
Agresi Militer Belanda I menjadi saksi bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan tidak mudah. Meski Indonesia menderita kerugian besar, serangan itu justru memperkuat posisi diplomasi Indonesia di mata dunia.
Pakar hubungan internasional Dr. Retno Marsudi (Menteri Luar Negeri RI) dalam pidatonya pada peringatan Hari Pahlawan 2020 menyatakan, “Agresi Militer Belanda I adalah titik balik yang memperlihatkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa yang tidak akan pernah tunduk pada penjajahan.”
Dengan semangat persatuan dan perjuangan diplomatik, bangsa Indonesia berhasil bertahan dan melangkah menuju pengakuan kedaulatan penuh pada 27 Desember 1949.
Baca juga: Sumpah Pemuda 1928: Tonggak Persatuan Menuju Indonesia Merdeka
![]()
![]()
![]()