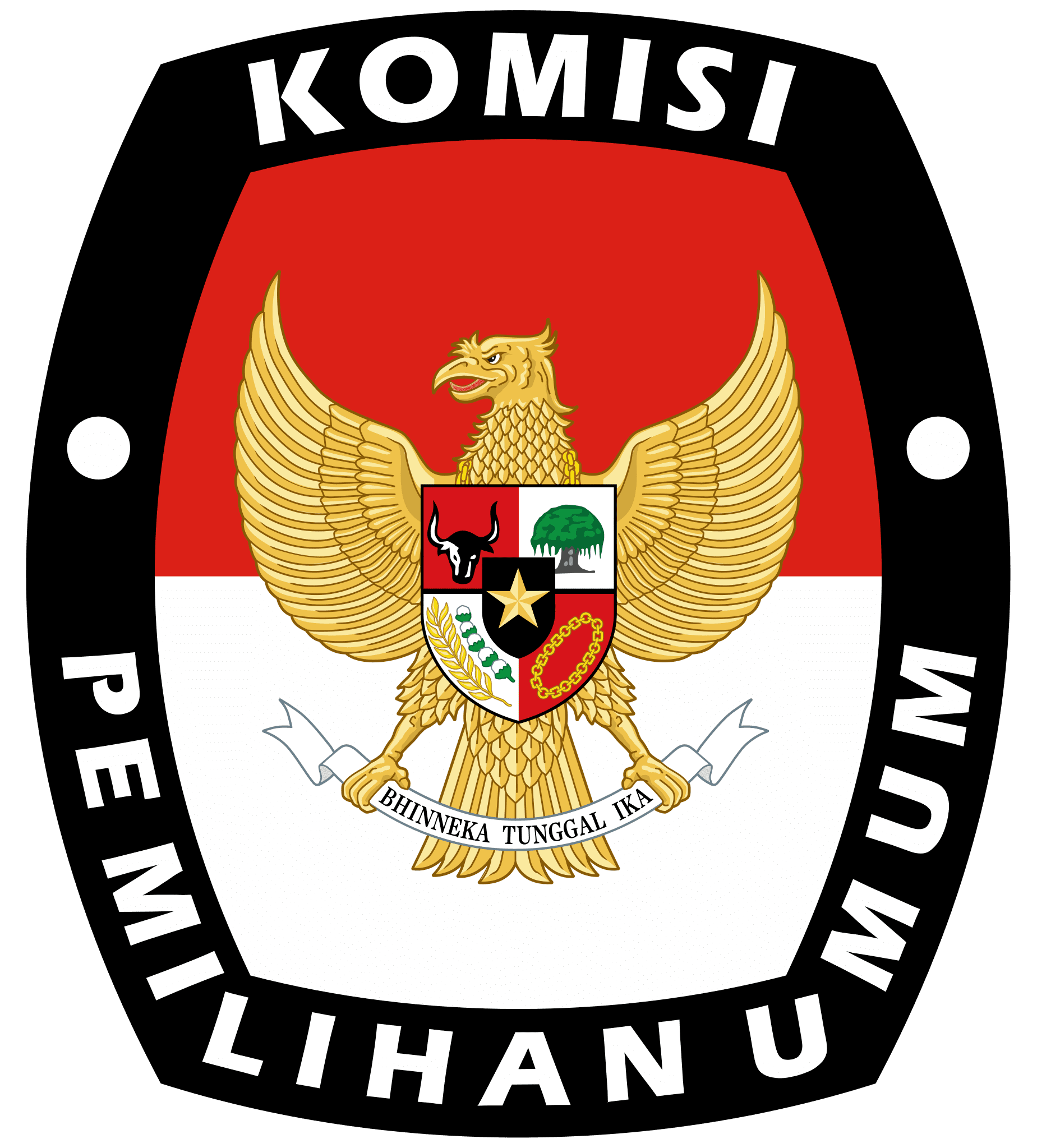Agresi Militer Belanda II: Serangan Mendadak yang Memicu Gelombang Perlawanan Nasional Indonesia
Wamena – Agresi Militer Belanda II merupakan salah satu babak kelam dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Serangan yang dilancarkan pada 19 Desember 1948 ini menjadi bukti nyata upaya Belanda untuk kembali menguasai Indonesia setelah perundingan diplomatik sebelumnya gagal. Peristiwa ini menandai pecahnya kembali konflik bersenjata antara Republik Indonesia dan Belanda setelah periode gencatan senjata pasca Perjanjian Renville.
Latar Belakang Serangan
Pasca Perjanjian Renville (17 Januari 1948), hubungan Indonesia–Belanda kembali tegang. Belanda menilai Republik Indonesia tidak mematuhi kesepakatan gencatan senjata, sementara Indonesia menuduh Belanda melakukan pelanggaran dan memperluas wilayah pendudukan.
Situasi memanas pada akhir 1948, ketika Belanda menuduh pemerintah Republik menyembunyikan kekuatan militer dan melakukan agitasi di daerah-daerah yang dikuasai Belanda. Dalam kondisi politik internasional yang belum stabil, Belanda kemudian melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Republik.
Sejarawan Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Asvi Warman Adam, menjelaskan dalam bukunya Sejarah Nasional Indonesia bahwa, “Agresi Militer Belanda II merupakan bentuk kegagalan diplomasi Belanda. Mereka ingin mematahkan eksistensi Republik Indonesia dengan kekuatan senjata, bukan melalui meja perundingan.”
Serangan ke Yogyakarta dan Penangkapan Pemimpin Republik
Pada pagi hari, 19 Desember 1948, pasukan Belanda melancarkan operasi militer dengan kode sandi “Operatie Kraai” (Operasi Gagak). Serangan dimulai dengan pengeboman Lapangan Terbang Maguwo, yang saat itu menjadi pangkalan utama Angkatan Udara Republik Indonesia. Dalam waktu singkat, Yogyakarta — ibu kota Republik — jatuh ke tangan Belanda.
Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta, dan beberapa pejabat tinggi lainnya ditangkap dan diasingkan ke Bangka serta Brastagi. Meski demikian, pemerintah Republik Indonesia menolak menyerah.
Sebelum ditangkap, Soekarno sempat menyampaikan pesan kepada rakyat melalui radio:
“Kepada seluruh rakyat Indonesia, teruskan perjuanganmu. Pemerintah mungkin ditawan, tetapi semangat kemerdekaan tidak akan pernah padam.” (Pidato Soekarno, Yogyakarta, 19 Desember 1948).
Lahirnya Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI)
Penangkapan para pemimpin negara tidak menghentikan perlawanan. Di bawah inisiatif Mr. Sjafruddin Prawiranegara, dibentuklah Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi, Sumatera Barat, pada 22 Desember 1948. Keberadaan PDRI menjadi simbol bahwa Republik Indonesia masih hidup. Menurut sejarawan Anhar Gonggong,
“PDRI adalah jantung Republik yang tetap berdetak di tengah penjajahan. Tanpa langkah cepat Sjafruddin, dunia mungkin mengira Indonesia sudah tiada.” (Sumber: Anhar Gonggong, Sejarah Nasional Indonesia, 2013). PDRI menjalankan fungsi pemerintahan, mengatur komunikasi dengan pasukan gerilya, serta menjaga hubungan diplomatik dengan dunia internasional.
Perlawanan Rakyat dan Strategi Gerilya
Pasca pendudukan Yogyakarta, pasukan Indonesia yang tersisa melanjutkan perjuangan dengan perang gerilya di berbagai daerah. Panglima Besar Jenderal Soedirman, meski sedang sakit parah, tetap memimpin perang dari pedalaman Jawa.
Jenderal Soedirman menegaskan dalam salah satu catatan perangnya:
“Selama rakyat Indonesia masih memiliki darah dan napas, perjuangan tidak akan berhenti. Tentara hanyalah bagian dari rakyat, dan rakyat adalah kekuatan sejati kemerdekaan.” (Dikutip dari Catatan Perang Gerilya Jenderal Soedirman, Arsip Nasional, 1949).
Strategi gerilya ini membuat Belanda kesulitan menguasai seluruh wilayah. Meski mereka berhasil menduduki kota-kota besar, daerah pedalaman tetap dikuasai oleh pejuang Republik. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara de facto, Belanda gagal menghancurkan Republik Indonesia.
Reaksi Dunia Internasional
Serangan Belanda terhadap Indonesia menimbulkan kecaman luas dari dunia internasional. Dewan Keamanan PBB segera menggelar sidang darurat dan menekan Belanda untuk menghentikan agresinya.
Negara-negara seperti India, Mesir, dan Australia menyatakan solidaritas terhadap perjuangan Indonesia. Tekanan diplomatik ini membuat Belanda akhirnya terpaksa menerima mediasi PBB melalui Komisi Tiga Negara (KTN) yang kemudian melahirkan Perundingan Roem–Royen pada Mei 1949.
Dalam perundingan tersebut, Belanda akhirnya setuju untuk membebaskan pemimpin Republik dan mengembalikan pemerintahan ke Yogyakarta.
Baca juga: Jejak Pahlawan di Meja Perundingan: Kisah Perjanjian Linggarjati
Dampak dan Akhir Agresi Militer Belanda II
Agresi Militer Belanda II justru memperkuat posisi Indonesia di mata dunia. Dunia internasional semakin simpati terhadap perjuangan rakyat Indonesia yang gigih mempertahankan kemerdekaannya.
Setelah tekanan internasional yang kuat, Belanda akhirnya bersedia menyerahkan kedaulatan melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag pada akhir 1949. Serangan militer yang semula dimaksudkan untuk menghancurkan Republik, justru menjadi bumerang bagi Belanda.
Agresi Militer Belanda II bukan sekadar peristiwa militer, tetapi simbol keteguhan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Dari Yogyakarta hingga pedalaman Jawa, dari Bukittinggi hingga Sumatera, semangat juang rakyat tidak pernah padam.
Sejarawan Dr. Bambang Purwanto dari Universitas Gadjah Mada menyimpulkan, “Agresi Militer Belanda II adalah bukti bahwa kemerdekaan Indonesia tidak diberikan, tetapi diperjuangkan dengan darah, diplomasi, dan keyakinan yang tak tergoyahkan.”
(Sumber: UGM Press, 2016).
![]()
![]()
![]()