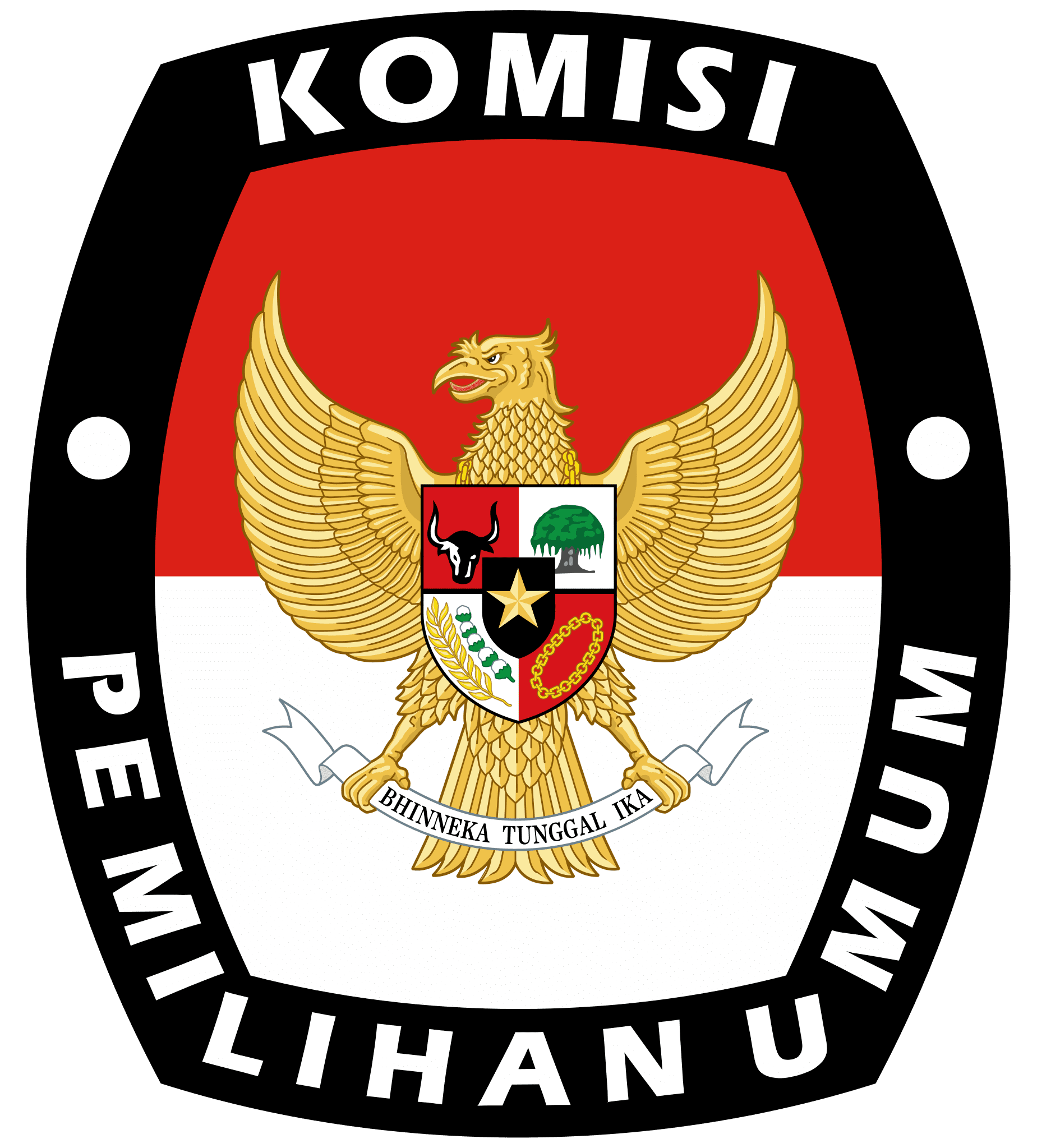Hak Ulayat adalah Wujud Kedaulatan Masyarakat Adat atas Tanah dan Alamnya
Wamena — Bagi masyarakat adat, tanah bukan hanya sekedar ruang hidup, tetapi menjadi sumber identitas, sejarah dan spiritual. Di banyak daerah di Indonesia, terutama di Papua, hubungan antara manusia dan tanah dijaga melalui sistem adat yang disebut dengan hak ulayat. Hak ulayat merepresentasikan bagaimana hubungan yang mendalam antara masyarakat dan sumber daya alam di wilayah mereka.
Pengertian Hak Ulayat Menurut Hukum dan Adat
Secara hukum adat, hak ulayat merupakan hak penguasaan bersama yang tertinggi atas wilayah tanah, air serta sumber daya alam di dalamnya, yang telah dikuasai dan dimanfaatkan secara turun-temurun oleh suatu kesatuan masyarakat hukum adat dan bersifat komunal.
Menurut Bambang S.Mulyono seorang ahli agraria, hak ulayat didefinisikan sebagai serangkaian wewenang dan kewajiban dari masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang berada di wilayahnya.
Setiap suku atau marga yang memiliki wilayah adat masing-masing dengan batas yang ditentukan oleh kesepakatan adat. Dalam pemanfaatan dan penggunaan tanah harus mendapatkan izin dari kepala suku atau dewan adat. Hak ulayat ini tidak dapat diperjualbelikan secara bebas karena dianggap sebagai warisan leluhur.
Baca juga: Demokrasi di Papua, Harmoni antara Musyawarah Adat, Sistem Noken, dan Nilai Kebersamaan
Hak ulayat memiliki ciri-ciri utama, yaitu:
- Hak Komunal: Dimiliki oleh persekutuan masyarakat adat, bukan individu.
- Hak Mengatur: Wewenang untuk mengatur penggunaan, peruntukan dan pemindahan hak atas tanah di wilayah tersebut.
- Hak Mengambil Manfaat: Kewenangan untuk mengambil hasil hutan, air dan Sumber Daya Alam lainnya.
Dasar Hukum Pengakuan Hak Ulayat di Indonesia
Pengakuan atas hak ulayat di Indonesia didasarkan pada pilar hukum utama:
- Konstitusi (UUD 1945) Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 secara eksplisit menyatakan:
“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”
- Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) adalah dasar hukum utama. Pasal 3 UUPA menyatakan:
“Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3) diakui hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataan masih ada. Penggunaannya harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, serta tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi”
Untuk hukum hak ulayat di wilayah Papua juga telah diatur dalam UU No. 21 Tahun 2002 tentang Otonomi Khusus papua yang dimana memberikan pengakuan khusus terhadap hak masyarakat adat Papua dalam mengelola sumber daya alam di wilayahnya.
Baca juga: Honai: Sejarah dan Perkembangan Rumah Adat Khas Papua yang Sarat Makna Budaya
Hak Ulayat di Tanah Papua: Identitas, Kearifan dan Tanggung Jawab Sosial
Di wilayah Fakfak, Asmat dan pegunungan Tengah, masyarakat adat memiliki sistem hukum yang kuat untuk melindungi hutan mereka dari eksploitasi berlebihan. Selain itu, hak ulayat memiliki kedudukan yang sangat kuat dan seringkali menjadi inti dari identitas, kearifan lokal dan tanggung jawab sosial masyarakat.
- Sistem Kepemilikan yang Kuat: Kepemilikan tanah ulayat di Papua, yang sering disebut sebagai Hak Ulayat Marga yang diakui secara tegas oleh setiap suku. Tanah bukan hanya asat ekonomi, tetapi juga tempat leluhur bersemayam dan sumber kehidupan spiritual.
- Kearifan Lokal: Kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya di Papua, seperti sistem sasi (larangan memanfaatkan hasil alam dalam periode tertentu), memastikan ekosistem tetap terjaga dari eksploitasi berlebihan.
- Tanggung Jawab Sosial: dalam konteks pembangunan dan investasi, perusahaan yang masuk ke tanah ulayat haruslah bernegosiasi dean memberikan kompensasi atau beneficial rights kepada pemilik hak ulayat. Hal ini untuk mencerminkan pengakuan bahwa pembangunan harus membawa manfaat langsung bagi masyarakat.
- Otonomi Khusus: Undang-Undang Otonomi Khusus Papua mengakui dan menghormati hak-hak dasar orang asli Papua, termasuk hak ulayat, yang seharusnya menjadi landasan kuat untuk perlindungan hukum
Peran Masyarakat Adat dalam Mengelola Tanah Ulayat
Peran masyarakat adat di tanah ulayat adalah sebagai pengatur dan pengelola utama. Mereka mengatur siapa yang boleh membuka lahan, berburu dan mengambil hasil hutan. Sistem ini diatur dalam hukum adat dan musyawarah adat, bukan melalui sertifikat formal seperti tanah milik negara. Sebagai contoh terdapat beberapa masyarakat adat yang mengelola tanah ualayat mereka, dianataranya:
- Di Suku Minangkabau, di sana tanah ulayat disebut dengan tanah kaum yang dimana tanah dimiliki oleh suatu kaum atau klan yang dikelola oleh ninik mamak untuk kepentingan keluarga besar atau kaum. Tanah kaum yang berupa lahan pertanian dan hutan tersebut digunakan suatu kaum yang berdasarkan pada garis keturunan matrilineal.
- Di Suku Dayak, tanah ulayat mencakup hutan adat yang dijaga oleh lembaga adat sendiri demi kepentingan ekosistem. Adanya perlindungan terhadap hutan dan kebun tradisional yang diwariskan secara turun-temurun.
- Masyarakat Bali, dikenal dengan ayahan desa, dimana tanah dikelola bersama oleh krama desa untuk kegiatan sosial dan keagamaan serta adanya sistem irigasi tradisional yang mengatur penggunaan air secara adil dan spiritual.
Tantangan Perlindungan Hak Ulayat di Era Modernisasi
|
Tantangan |
Deskripsi |
Solusi yang Diusulkan |
|
Tumpang Tindih Perizinan |
Pemberian izin konsesi (HPH, pertambangan, perkebunan) oleh pemerintah sering adanya tumpang tindih dengan wilayah ulayat yang belum dipetakan. |
Harus adanya Percepatan Pemetaan Partisipatif atau pemetaan wilayah adat yang melibatkan masyarakat dan penetapan melalui sebuah peraturan daerah ataupun menteri. |
|
Absennya Regulasi Pelaksana |
Belum adanya undang-undang tunggal yang secara khusus mengatur dan menguatkan Hak Masyarakat Adat sehingga membuat perlindungan hukum lemah. |
Pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat untuk memberikan kepastian hukum dan prosedur pengakuan. |
|
Asas Kepentingan Nasional |
Penerapan asa “kepentingan nasional” sering digunakan untuk mengesampingkan hak ulayat demi proyek infrastruktur atau investasi dalam skala yang besar. |
Harus adanya Persetujuan Tanpa Paksaan Sebelumnya dan Diberitahukan (PPSP) setiap adanya proyek yang menyentuh wilayah adat. |
Hak ulayat bukanlah menjadi hambatan bagi pembangunan, melainkan dasar moral untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Berbagai upaya terus dilakukan untuk bisa menjaga hak ulayat. Pemerintah dan AMAN (Aliansi Masyarakat Adat nusantara) serta berbagai organisasi lokal mendorong pemetaan partisipatif wilayah adat serta pengakuan peraturan daerah untuk melindungi hak ulayat ini. Ketika negara menghormati hak adat, pembangunan bisa berjalan tanpa adanya mengorbankan kearifan lokal dan keasrian alam.
Baca juga: Rumah Adat Papua: Jenis, Fungsi, Keunikan dan Filosofi
![]()
![]()
![]()