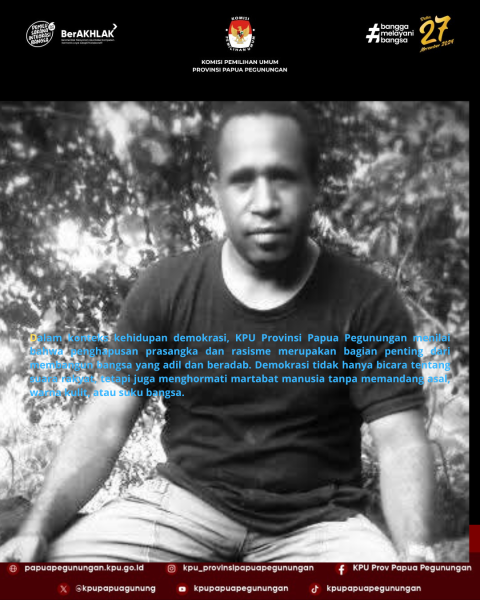
KPU Provinsi Papua Pegunungan: Eugenics Adalah Awal Tindakan Rasisme
Wamena – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Pegunungan menyoroti pentingnya pemahaman sejarah sosial dan moral untuk memperkuat nilai kemanusiaan dan keadilan dalam kehidupan berdemokrasi. Salah satu topik yang relevan dalam konteks tersebut adalah eugenics—sebuah gagasan yang menjadi awal mula munculnya praktik rasisme di dunia modern.
Kata eugenics berasal dari bahasa Yunani yang berarti “dilahirkan secara baik”. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1883 oleh Sir Francis Galton, seorang dokter asal Inggris sekaligus sepupu dari ilmuwan terkenal Charles Darwin. Galton berkeyakinan bahwa sifat-sifat manusia diwariskan secara biologis dari orang tua kepada anak, dan tidak bergantung pada pendidikan atau lingkungan. Ia berpendapat bahwa manusia dapat “memperbaiki rasnya” dengan cara mengatur perkawinan secara selektif — hanya orang-orang yang dianggap memiliki sifat “baik” yang diperbolehkan memiliki keturunan.
Pemikiran Galton sangat dipengaruhi teori evolusi Darwin, khususnya prinsip survival of the fittest — hanya yang kuat dan sehat yang dapat bertahan hidup. Dari sini, ia berasumsi bahwa perkawinan yang selektif akan melahirkan manusia-manusia “unggul”. Namun muncul pertanyaan mendasar: siapa yang berhak menentukan siapa yang unggul dan siapa yang tidak?
Pemikiran inilah yang kemudian diadopsi secara ekstrem oleh kaum Nazi di Jerman. Mereka menetapkan ras “Arya” sebagai manusia terbaik, sementara orang Yahudi dan kelompok lain dianggap inferior. Pemerintah Nazi bahkan membuat aturan yang melarang hubungan antara orang Arya dengan non-Arya. Dalam praktiknya, ribuan orang Yahudi dibunuh, dan anak-anak dengan ciri ras “murni” diambil dari keluarganya untuk dijadikan anak angkat oleh keluarga Nazi.
Tragedi ini menjadi bukti bahwa gagasan eugenika dapat melahirkan kejahatan kemanusiaan ketika disalahgunakan untuk menjustifikasi diskriminasi rasial.
Tidak hanya di Jerman, pada awal abad ke-20 Amerika Serikat juga memberlakukan hukum yang melarang perkawinan antara orang kulit hitam dan kulit putih, sementara di Afrika Selatan, sistem apartheid secara resmi memisahkan kelompok ras dalam kehidupan sosial dan politik.
Para ilmuwan sosial kemudian membantah dasar ilmiah eugenika. Mereka menegaskan bahwa perbedaan genetik antar manusia sangat kecil, sehingga tidak ada ras manusia yang benar-benar superior. Ilmu pengetahuan modern membuktikan bahwa seluruh manusia termasuk dalam satu spesies yang sama, yaitu Homo sapiens. Karena itu, istilah yang lebih tepat digunakan adalah kelompok etnis, bukan “ras”.
Sikap rasis sendiri bukanlah sifat bawaan manusia, tetapi hasil dari pembelajaran sosial. Anak-anak kecil tidak memiliki prasangka; mereka belajar menjadi rasis dari lingkungan sekitar. Rasisme sering kali tumbuh dari rasa takut terhadap perbedaan atau dari keinginan untuk menyalahkan “kelompok luar” atas masalah yang dihadapi, seperti kemiskinan atau pengangguran.
Selain itu, manusia cenderung memproyeksikan sisi negatif dirinya kepada orang lain. Dengan menganggap orang lain malas, bodoh, atau berbahaya, seseorang merasa lebih baik dan lebih “unggul”. Pandangan ini yang kemudian menumbuhkan rasa superioritas rasial, seksisme, serta diskriminasi sosial.
Dalam konteks kehidupan demokrasi, KPU Provinsi Papua Pegunungan menilai bahwa penghapusan prasangka dan rasisme merupakan bagian penting dari membangun bangsa yang adil dan beradab. Demokrasi tidak hanya bicara tentang suara rakyat, tetapi juga menghormati martabat manusia tanpa memandang asal, warna kulit, atau suku bangsa.
Melalui refleksi atas sejarah kelam eugenika, kita diingatkan bahwa pengetahuan tanpa nilai kemanusiaan dapat membawa kehancuran. Oleh karena itu, penting bagi setiap warga negara, termasuk penyelenggara pemilu, untuk menanamkan nilai persaudaraan, kesetaraan, dan penghargaan terhadap keberagaman sebagai wujud nyata dari demokrasi Pancasila.
Ditulis Oleh :
Papson Hilapok
![]()
![]()
![]()
