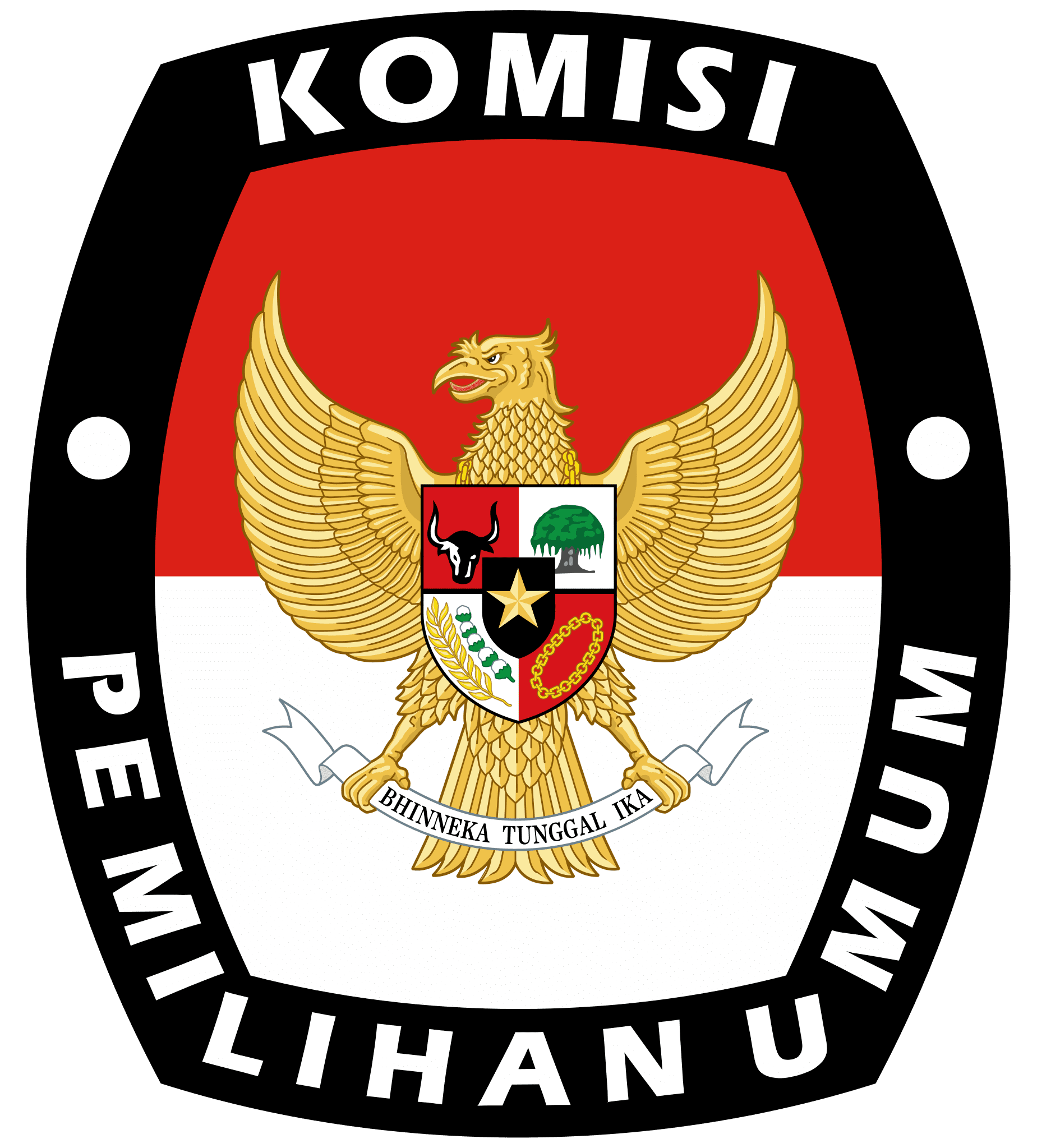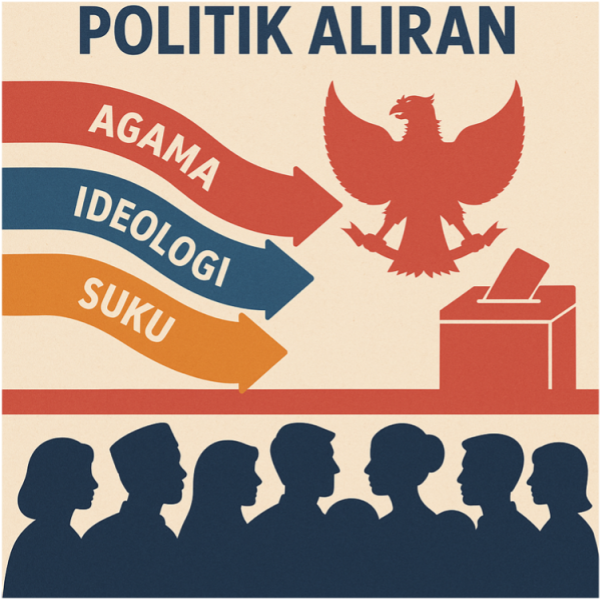
Politik Aliran: Pengertian, Contoh, dan Dampaknya di Indonesia
Wamena — Politik aliran masih menjadi fenomena menarik dalam kehidupan politik Indonesia. Meskipun istilahnya sudah muncul sejak masa awal kemerdekaan, pengaruhnya tetap terasa hingga kini — terutama ketika pesta demokrasi digelar. Politik aliran mencerminkan bagaimana identitas sosial, agama, hingga ideologi dapat membentuk arah dukungan politik masyarakat.
Pengertian Politik Aliran Menurut Para Ahli
Secara umum, politik aliran (political stream) adalah pola perilaku politik masyarakat yang didasarkan pada ikatan ideologis, agama, suku, atau kelompok sosial tertentu.
Ilmuwan politik Belanda, Clifford Geertz, menyebut politik aliran sebagai manifestasi dari “subkultur politik” — di mana masyarakat cenderung memilih dan mendukung partai yang dianggap mewakili nilai-nilai kelompoknya.
Sementara itu, Herbert Feith menilai politik aliran di Indonesia muncul karena keberagaman masyarakat yang tinggi, sehingga pilihan politik sering kali mengikuti garis sosial dan budaya yang telah mengakar.
Baca juga: Politik: Makna, Fungsi, dan Dampaknya bagi Kehidupan Rakyat
Sejarah dan Asal-usul Politik Aliran di Indonesia
Akar politik aliran di Indonesia dapat ditelusuri sejak masa pergerakan nasional.
Pada masa itu, organisasi seperti Sarekat Islam (SI), Partai Nasional Indonesia (PNI), dan Partai Katolik muncul dengan basis massa yang kuat dari kelompok sosial tertentu.
Pasca kemerdekaan, politik aliran makin menguat pada era Demokrasi Liberal (1950–1959), ketika partai-partai seperti Masyumi, NU, PSI, dan PKI memiliki pengikut yang jelas dari kalangan keagamaan maupun ideologis.
Meskipun sistem multipartai kemudian disederhanakan pada masa Orde Baru, akar-akar politik aliran tidak sepenuhnya hilang — hanya tersamarkan di balik sentralisasi kekuasaan.
Contoh Politik Aliran di Indonesia
Politik aliran masih dapat ditemukan dalam dinamika politik modern, meski dalam bentuk yang lebih halus.
Misalnya, dukungan terhadap partai berbasis Islam, nasionalis, atau kedaerahan sering kali mencerminkan preferensi identitas kelompok.
Di beberapa daerah, kecenderungan memilih kandidat berdasarkan etnis atau agama juga masih terlihat, terutama dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Fenomena ini menunjukkan bahwa, meskipun masyarakat makin rasional dalam menentukan pilihan, faktor identitas masih menjadi pertimbangan penting.
Baca juga: Pengertian Politik: Arti, Tujuan, Konsep, dan Contoh dalam Kehidupan Sehari-hari
Dampak Politik Aliran terhadap Demokrasi dan Pemilu
Politik aliran memiliki dua sisi mata uang.
Di satu sisi, ia memperkaya demokrasi dengan keberagaman aspirasi. Setiap kelompok merasa terwakili dalam sistem politik.
Namun di sisi lain, politik aliran juga berpotensi memecah belah jika tidak dikelola dengan bijak. Polarisasi berbasis agama atau etnis bisa memperlemah semangat kebangsaan, terutama ketika kontestasi politik lebih menonjolkan “kami” dan “mereka” daripada ide dan gagasan.
Kondisi ini bisa mengganggu integritas pemilu dan mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara maupun hasilnya.
Tantangan Politik Aliran di Era Modern
Di era digital seperti sekarang, politik aliran menghadapi bentuk baru: politik identitas di media sosial.
Algoritma media digital cenderung memperkuat pandangan kelompok tertentu (echo chamber), membuat masyarakat terjebak dalam opini yang homogen.
Hal ini menantang pendidikan politik di Indonesia — bagaimana mendorong masyarakat berpikir kritis tanpa kehilangan akar budaya dan keyakinannya.
Tantangan lainnya adalah menjaga ruang publik agar tetap inklusif, di tengah meningkatnya ujaran kebencian dan hoaks bernuansa SARA menjelang pemilu.
Baca juga: Incumbent Adalah: Pengertian, Arti, dan Contohnya dalam Politik
Peran KPU dalam Menjaga Netralitas di Tengah Politik Aliran
Sebagai penyelenggara pemilu, KPU memiliki peran vital dalam memastikan setiap proses berjalan adil, netral, dan transparan, terlepas dari kuatnya arus politik aliran.
Melalui sosialisasi, pendidikan pemilih, dan pengawasan tahapan, KPU berupaya membangun kesadaran politik yang rasional dan inklusif.
Netralitas penyelenggara menjadi benteng terakhir agar pemilu tidak hanya menjadi arena perebutan kekuasaan berbasis identitas, tetapi benar-benar menjadi pesta demokrasi untuk semua warga negara.
![]()
![]()
![]()