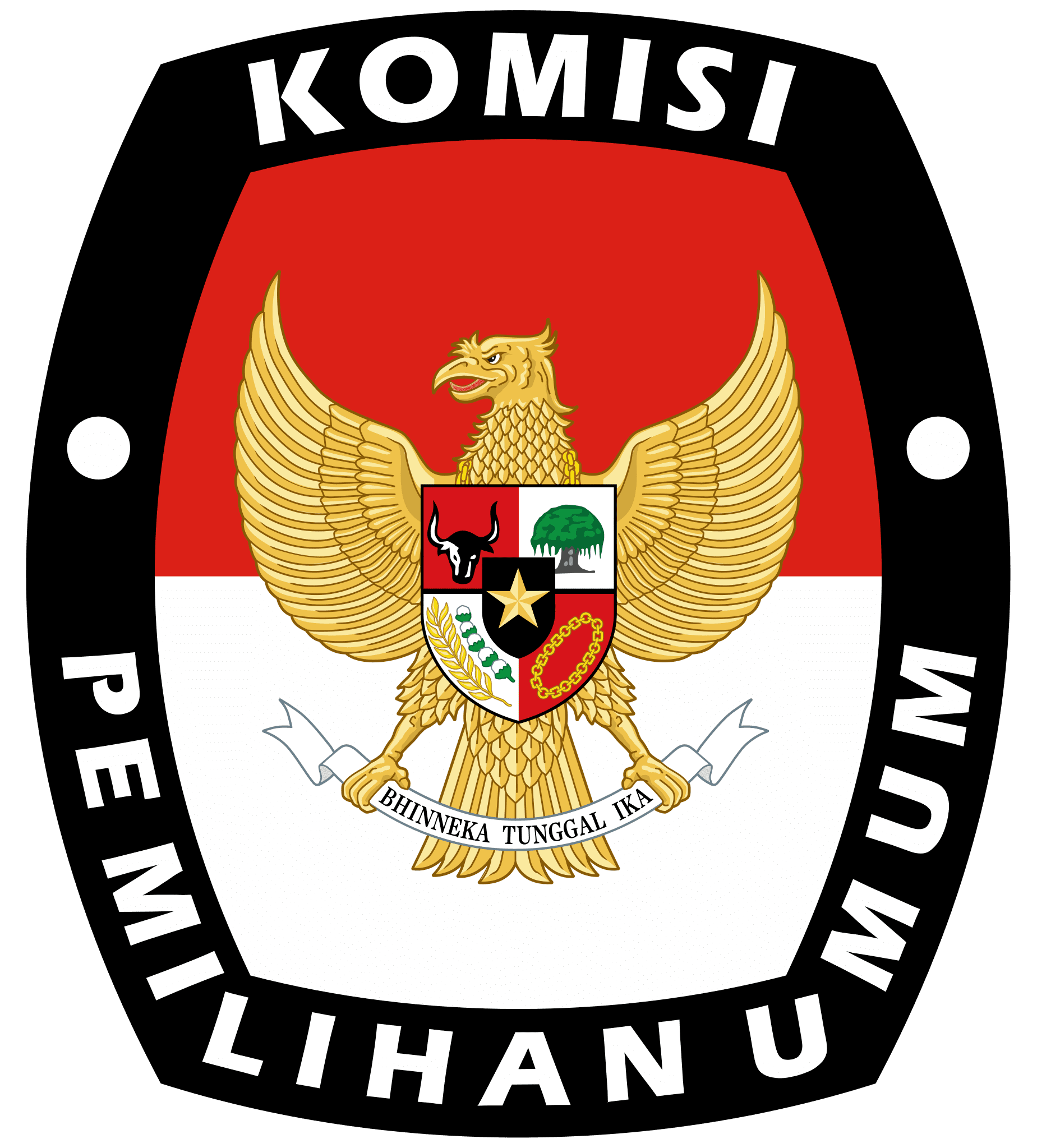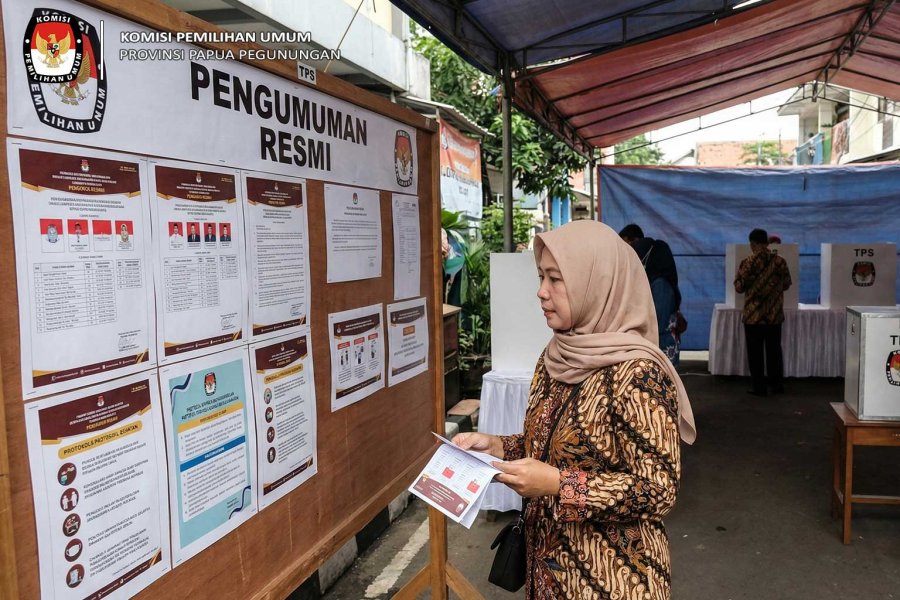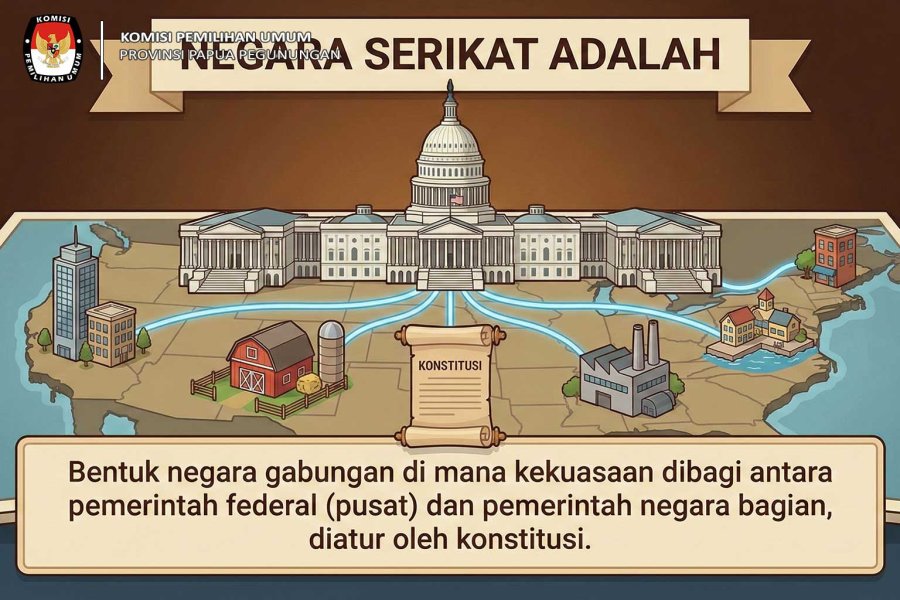Desa Adalah: Pengertian, Ciri, dan Perannya dalam Pemerintahan Indonesia
Kobagma - Pernahkah Anda bertanya, di mana sesungguhnya letak jantung demokrasi dan pembangunan Indonesia berdetak paling kencang? Jawabannya bukan hanya di gedung-gedung tinggi ibu kota, melainkan di ribuan unit pemerintahan terkecil yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, termasuk di lembah-lembah pegunungan kita. Unit tersebut adalah desa. Namun, seberapa dalam kita memahami entitas ini? Apakah desa hanya sekadar sekumpulan rumah di pedalaman, ataukah ia memiliki kedaulatan tersendiri? Memahami definisi dan fungsi desa bukan hanya tugas aparat pemerintah, melainkan kewajiban setiap warga negara yang sadar akan hak politiknya. Artikel ini akan mengupas tuntas bahwa desa adalah fondasi utama dalam struktur ketahanan nasional dan demokrasi Indonesia. Pengertian Desa Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Secara terminologi hukum, definisi yang paling valid dan menjadi rujukan utama saat ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam regulasi tersebut, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Definisi ini membawa perubahan paradigma yang sangat besar. Sebelum adanya UU Desa, desa seringkali hanya dianggap sebagai objek pembangunan atau kepanjangan tangan administratif dari pemerintah kabupaten/kota. Namun, dengan UU ini, desa diakui sebagai subjek yang berdaya. Poin penting dari pengertian di atas meliputi: Kesatuan Masyarakat Hukum: Desa bukan sekadar wilayah geografis, tetapi entitas manusia yang terikat oleh aturan hukum dan adat istiadat. Otonomi Asli: Desa memiliki kewenangan mengatur rumah tangganya sendiri (hak asal-usul). Di wilayah seperti Papua Pegunungan, ini sangat relevan dengan eksistensi "Kampung" atau sebutan lokal lainnya yang diakui negara. Pengakuan Negara: Meski otonom, desa tetap berada dalam bingkai NKRI, menjamin keselarasan antara hukum adat dan hukum positif nasional. Baca juga: Perbedaan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota: Kewenangan, Wilayah, dan Cara Pemilihannya Ciri-Ciri Desa: Antara Sosiologis dan Administratif Untuk membedakan desa dengan kelurahan atau unit perkotaan lainnya, kita perlu memahami karakteristik yang melekat padanya. Ciri-ciri desa dapat ditinjau dari dua aspek: sosiologis dan administratif. Ciri-Ciri Sosiologis (Karakteristik Masyarakat): Gemeinschaft (Paguyuban) Hubungan antarwarga sangat erat, bersifat kekeluargaan, dan gotong royong masih menjadi nafas utama kehidupan sehari-hari. Homogenitas Meskipun zaman berkembang, masyarakat desa cenderung memiliki kesamaan dalam mata pencaharian (umumnya agraris atau nelayan), nilai kebudayaan, dan adat istiadat. Kedekatan dengan Alam Kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat desa sangat bergantung pada potensi alam sekitarnya. Kontrol Sosial yang Kuat Norma dan adat istiadat memegang peranan penting dalam menjaga ketertiban, seringkali lebih efektif daripada hukum tertulis. Unsur Pembentuk Desa (Secara Administratif): Agar dapat disebut sebagai desa yang sah, harus terpenuhi tiga unsur mutlak: Wilayah: Memiliki batas-batas geografis yang jelas (tanah, hutan, perairan). Penduduk: Terdapat sekelompok manusia yang menetap di wilayah tersebut. Pemerintahan: Adanya struktur organisasi yang mengatur tata kelola kehidupan masyarakat. Fungsi dan Peran Desa dalam Pembangunan Nasional Desa tidak berdiri pasif. Berdasarkan undang-undang, desa mengemban empat mandat utama yang menjadi pilar perannya dalam pemerintahan Indonesia. 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Desa berfungsi sebagai unit pemerintahan terdepan yang melayani administrasi kependudukan dasar. Mulai dari surat pengantar, data kelahiran, hingga kematian, semua bermula dari data desa. Desa memastikan kehadiran negara di pelosok terpencil. 2. Pelaksanaan Pembangunan Desa Dengan adanya Dana Desa, desa kini berperan sebagai eksekutor pembangunan. Pembangunan ini tidak hanya fisik (jalan desa, jembatan, irigasi), tetapi juga pembangunan sarana prasarana kesehatan (Posyandu) dan pendidikan (PAUD). Tujuannya adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat secara mandiri. 3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa Desa berperan menjaga ketenteraman dan ketertiban. Peran ini mencakup pelestarian adat istiadat, penguatan kerukunan umat beragama, dan menjaga stabilitas sosial agar konflik horizontal dapat diredam sejak dini. 4. Pemberdayaan Masyarakat Desa Ini adalah fungsi strategis untuk memandirikan warga. Desa memfasilitasi pelatihan keterampilan, mendukung BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), dan menciptakan peluang ekonomi agar masyarakat tidak perlu urbanisasi untuk mencari nafkah. Baca juga: Kotak Kosong Menang di Pilkada, Apa yang Terjadi Selanjutnya? Pemerintahan Desa dan Lembaga-Lembaganya (Demokrasi Lokal) Dalam menjalankan fungsinya, Pemerintahan Desa tidak bekerja sendirian. Terdapat sistem check and balances yang mencerminkan demokrasi skala lokal. Pemerintah Desa Terdiri dari Kepala Desa (atau sebutan lain seperti Kepala Kampung) yang dibantu oleh Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan). Mereka adalah lembaga eksekutif yang menjalankan roda pemerintahan sehari-hari. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ini adalah lembaga legislatif di tingkat desa. Anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis. Fungsi BPD sangat krusial: membahas dan menyepakati Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung aspirasi masyarakat, dan mengawasi kinerja Kepala Desa. Musyawarah Desa (Musdes) Ini adalah forum tertinggi dalam pengambilan keputusan strategis desa. Musdes adalah wujud nyata dari sila ke-4 Pancasila, di mana keputusan diambil melalui hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Desa dan Partisipasi Warga dalam Pemilu Sebagai KPU, sangat penting untuk menegaskan bahwa kualitas demokrasi nasional sangat bergantung pada apa yang terjadi di desa. Desa adalah ujung tombak kesuksesan Pemilihan Umum (Pemilu) maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Peran Desa dalam Ekosistem Pemilu: Basis Data Pemilih Validitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) dimulai dari pemutakhiran data di tingkat desa/kelurahan. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) bekerja menyisir rumah ke rumah di desa untuk memastikan hak pilih warga terlindungi. Penyelenggara Ad Hoc Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) adalah warga desa setempat. Mereka adalah garda terdepan yang menjaga kemurnian suara rakyat di TPS. Pendidikan Politik Desa adalah ruang kelas demokrasi yang paling efektif. Melalui forum warga, sosialisasi mengenai pentingnya memilih dan menolak politik uang (money politics) dapat dilakukan dengan pendekatan kultural yang lebih menyentuh hati. Stabilitas Keamanan Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) di desa berperan vital dalam menjaga kondusivitas saat hari pemungutan suara. Masyarakat desa yang cerdas dan partisipatif akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Sebaliknya, jika masyarakat desa apatis, maka fondasi demokrasi negara akan rapuh. Oleh karena itu, partisipasi aktif warga desa—bukan hanya saat mencoblos, tapi juga dalam mengawasi tahapan pemilu—adalah kunci tegaknya kedaulatan rakyat. Baca juga: Mengapa Papua Pakai Distrik, Bukan Kecamatan? Ini Penjelasan Lengkapnya Memahami bahwa desa adalah entitas yang berdaulat, memiliki otonomi, dan memegang peran vital, seharusnya mengubah cara pandang kita. Desa bukan sekadar tempat tinggal, melainkan arena di mana pembangunan dimulai dan demokrasi dipraktikkan setiap hari. Dari definisi hukum hingga realitas sosial, desa membuktikan dirinya sebagai benteng pertahanan sosial, ekonomi, dan politik bangsa. Khususnya bagi kita di Provinsi Papua Pegunungan, desa atau kampung adalah identitas. Partisipasi aktif kita dalam membangun desa dan menyukseskan agenda demokrasi seperti Pemilu adalah wujud cinta tanah air yang paling nyata. Mari kita jadikan desa sebagai titik tolak kemajuan. Jangan hanya menjadi penonton; libatkan diri Anda dalam Musyawarah Desa, awasi penggunaan Dana Desa, dan pastikan nama Anda terdaftar sebagai pemilih tetap. Sebab pada akhirnya, desa yang kuat akan menopang negara yang berdaulat. Desa mawa cara, negara mawa tata—desa memiliki adatnya, negara memiliki aturannya; keduanya bersatu membangun Indonesia Raya. Sudahkah Anda berkontribusi untuk desa Anda hari ini? Referensi: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa. Modul Tata Kelola Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri.