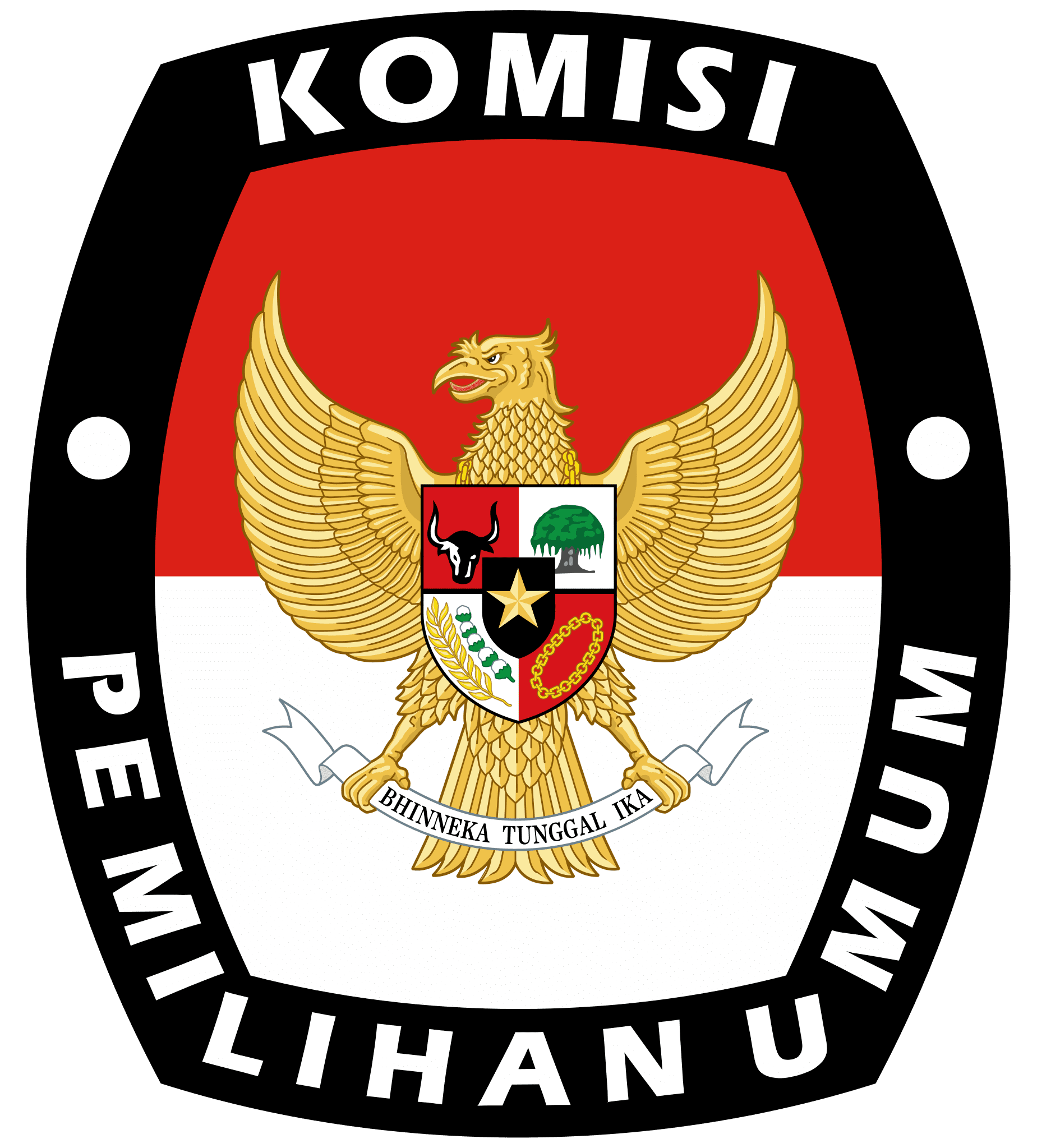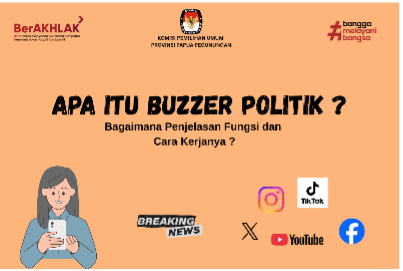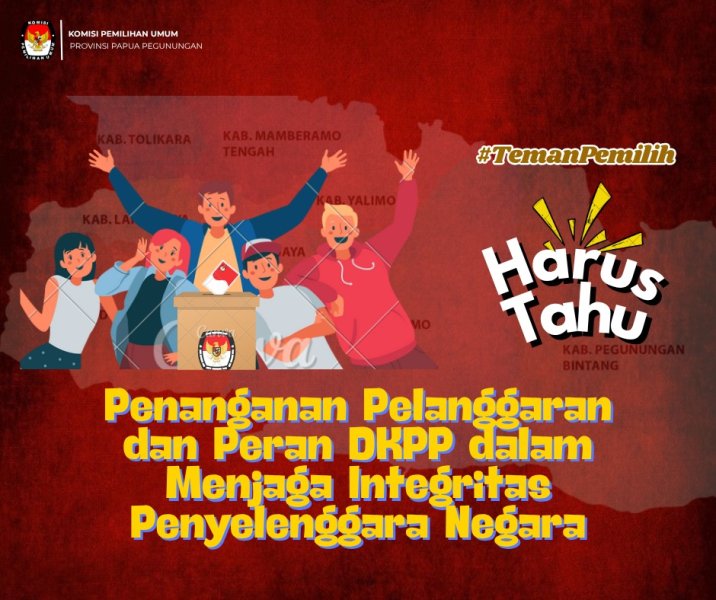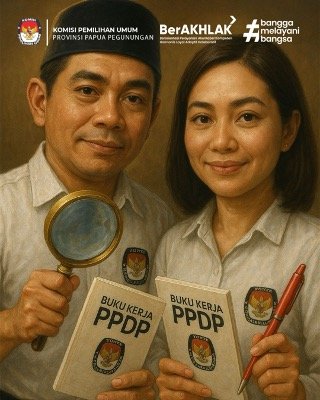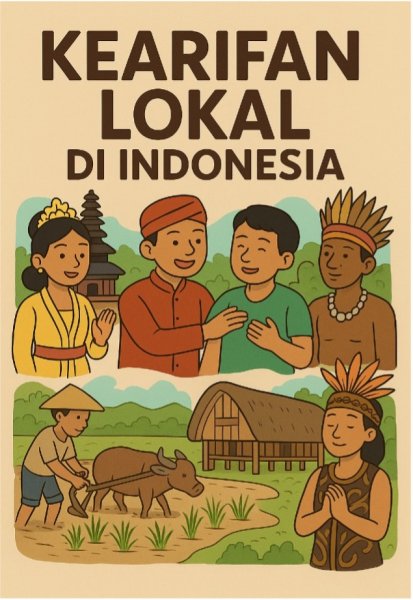Dari Sumpah Pemuda ke KTT ASEAN 2025: Membangun Inklusivitas dan Keberlanjutan dari Timur Indonesia
Wamena — Ketika bangsa Indonesia memperingati Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober, dunia juga menyorot kawasan Asia Tenggara melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2025 yang mengusung tema “Inclusivity and Sustainability.” Dua momentum besar ini seolah berpadu dalam satu napas perjuangan: semangat untuk merangkul semua perbedaan dan menjaga keberlanjutan masa depan. Bagi Indonesia, nilai-nilai tersebut bukan hal baru — ia telah tertanam sejak para pemuda 1928 menyatukan tekad untuk satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Kini, tugas generasi muda adalah melanjutkan semangat itu dalam konteks demokrasi modern yang inklusif dan berkelanjutan. Baca juga: Dari Medan Juang ke Demokrasi: Teladan Nasionalisme Prabowo Sumpah Pemuda: Akar Inklusivitas Bangsa Sumpah Pemuda menjadi tonggak penting dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Pada 28 Oktober 1928, para pemuda dari berbagai latar belakang suku, bahasa, dan daerah berkumpul dalam satu tekad: Indonesia harus berdiri sebagai bangsa yang satu. Di tengah kolonialisme dan keterpecahan sosial saat itu, para pemuda telah menanam nilai yang kini kita sebut sebagai inklusivitas — pengakuan bahwa setiap anak bangsa memiliki ruang yang sama untuk berkontribusi. Nilai ini sangat relevan dengan semangat Inclusivity yang diangkat dalam KTT ASEAN 2025. Di tingkat regional, inklusivitas bermakna membangun kawasan yang terbuka bagi semua negara anggota, tanpa memandang besar atau kecilnya ekonomi dan pengaruh politik. Begitu pula di Indonesia, semangat Sumpah Pemuda mengajarkan bahwa kemajuan bangsa hanya dapat dicapai jika semua warganya, dari Sabang hingga Pegunungan Papua, memiliki kesempatan yang setara dalam pendidikan, ekonomi, dan politik. Dalam konteks demokrasi, inklusivitas juga berarti membuka ruang partisipasi yang adil bagi setiap warga negara, tanpa diskriminasi dan tanpa batasan geografis. Baca juga: Agus Filma: Dari Biak Timur untuk Demokrasi di Papua Pegunungan Dari Persatuan Nasional ke Solidaritas Regional Sumpah Pemuda telah menjadi fondasi bagi lahirnya semangat solidaritas nasional. Kini, semangat itu meluas ke tingkat kawasan melalui kerja sama ASEAN. Tema “Inclusivity and Sustainability” bukan sekadar jargon diplomatik, melainkan cerminan dari upaya kolektif negara-negara Asia Tenggara untuk membangun masa depan bersama. Indonesia, sebagai salah satu pendiri ASEAN, memiliki tanggung jawab moral dan sejarah untuk membawa nilai-nilai persatuan dan gotong royong ke dalam kebijakan regional. Bagi pemuda Indonesia, terutama generasi digital masa kini, solidaritas regional bisa diwujudkan melalui kolaborasi lintas batas: pertukaran ide, inovasi teknologi, dan kerja sama sosial. Ketika pemuda Indonesia berperan aktif dalam isu-isu seperti perubahan iklim, ekonomi hijau, dan transformasi digital, mereka sejatinya sedang melanjutkan semangat para pemuda 1928 — hanya dalam bentuk perjuangan yang lebih modern. Dari kampus di Jakarta hingga sekolah di pegunungan Wamena, semangat persatuan itu tetap sama: menciptakan masa depan Asia Tenggara yang damai, inklusif, dan berkeadilan. Baca juga: Kasman Singodimejo: Jembatan Persatuan dari Sumpah Pemuda hingga Dasar Negara Keberlanjutan sebagai Tanggung Jawab Generasi Muda Selain inklusivitas, sustainability atau keberlanjutan menjadi nilai penting yang diangkat dalam KTT ASEAN tahun ini. Keberlanjutan bukan hanya tentang menjaga lingkungan, tetapi juga memastikan kesejahteraan sosial dan politik dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Di Indonesia, nilai ini sejalan dengan cita-cita para pendiri bangsa sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.” Generasi muda Indonesia kini dihadapkan pada tantangan baru — dari perubahan iklim hingga tantangan moral dalam demokrasi digital. Namun, di balik tantangan itu terdapat peluang besar untuk membangun bangsa yang tangguh dan berdaya saing. Pemuda dan ASN, termasuk yang bertugas di Papua Pegunungan, dapat menjadi teladan dalam menerapkan nilai keberlanjutan melalui kerja nyata: menjaga integritas dalam pemilu, berinovasi di bidang energi terbarukan, serta mengedepankan prinsip keadilan sosial bagi masyarakat di pelosok negeri. Baca juga: Purbaya Yudhi Sadewa: Ekonom Visioner di Balik Arah Baru Pembangunan Nasional Menjaga Semangat Persatuan dalam Demokrasi Demokrasi Indonesia hari ini adalah kelanjutan dari semangat Sumpah Pemuda yang dihidupkan dalam konteks modern. Melalui mekanisme pemilu yang jujur dan transparan, rakyat Indonesia diberi kesempatan untuk bersuara dan menentukan arah masa depan bangsanya. Inilah bentuk nyata inklusivitas dan keberlanjutan dalam sistem politik — di mana setiap suara rakyat, tanpa memandang latar belakang, memiliki nilai yang sama. Seperti halnya WR. Supratman yang menyatukan bangsa lewat lagu Indonesia Raya, kini rakyat menyatukan negeri lewat suara yang jujur dalam setiap pemilu. Di Papua Pegunungan, semangat itu tampak ketika masyarakat berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi, menjadikan daerah paling timur Indonesia sebagai bagian penting dari perjalanan nasional. Dari timur hingga barat, dari laut hingga pegunungan, semangat persatuan itu terus hidup dalam denyut demokrasi Indonesia yang terus berkembang. Baca juga: KH. Wahid Hasyim : Ulama, Negarawan, dan Pelopor Semangat Demokrasi Indonesia Penutup Reflektif: Pemuda dan Masa Depan yang Inklusif Sumpah Pemuda dan KTT ASEAN 2025 sama-sama mengajarkan bahwa masa depan hanya bisa dibangun di atas pondasi inklusivitas dan keberlanjutan. Bagi bangsa Indonesia, kedua nilai ini bukan hanya isu global, melainkan identitas nasional yang telah diwariskan sejak 1928. Pemuda Indonesia hari ini memegang peran strategis — menjadi penjaga semangat demokrasi, pelindung lingkungan, dan pelopor kemajuan bangsa. Dari Jayapura hingga Jakarta, dari Pegunungan Cartenz hingga perbatasan Kalimantan, pemuda Indonesia harus terus membawa pesan yang sama: persatuan dalam keberagaman, dan keberlanjutan untuk generasi masa depan. Karena sebagaimana para pendahulu meneguhkan Sumpah Pemuda dengan tekad yang bulat, kini generasi muda meneguhkannya kembali dalam tindakan nyata — menjaga inklusivitas dan keberlanjutan bagi Indonesia dan dunia. -Pram- Rujukan: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kementerian Luar Negeri RI – Chairmanship ASEAN 2025: Inclusivity and Sustainability. Arsip Nasional Republik Indonesia – Kongres Pemuda II dan Sumpah Pemuda 1928. KPU RI – Partisipasi Rakyat dalam Demokrasi Indonesia